Penulis : M.Syamsudini, M,Ag
Abstrak
Di era multikulturalisme dan pluralisme, pendidikan Islam sedang mendapat tantangan karena ketidakmampuannya dalam membebaskan peserta didik keluar dari ekslusivitas beragama. Wacana kafir-iman, muslim-non muslim, sorga-neraka sering kali menjadi bahan pelajaran di kelas yang selalu diindoktrinasi. Pelajaran teologi diajarkan hanya sekedar untuk memperkuat keimanan dan pencapainannya menuju menuju sorga tanpa dibarengi kesadaran berdialog dengan agama-agama lain. Di sekolah-sekolah Islam dari levelnya yang paling bawah ( Pendidikan Anak Usia Dini /PAUD ) samapai keperguruan tinggi, fenomena ini tumbuh subur. Pendidikan Islam yang ekslusif-doktrinal ini telah menciptakan kesadaran umatnya untuk memandang agama lain secara amat berbeda, bahkan bermusuhan. Kondisi inilah yang menjadikan pendidikan Islam sangat ekslusif dan tidak toleran terhadap pendidikan agama lain. Padahal di era multikulturalisme dewasa ini, pendidikan Islam mesti melakukan reorientasi filosofis-paradigmatik tentang bagaimana membentuk kesadaran peserta didiknya berwajah inklusif dan toleran. Inilah tantangan serius dalam mengembangkan pendidikan Islam.
Kata kunci : Multikulturalisme, Pendidikan Islam, reorientasi.
Pendahuluan
Dialog antar umat beragama belum lama dilakukan di Indonesia, begitu juda pada level internasional. Baru tahun 1970-an Departemen Agama Republik Indonesia menyelenggarakan forum-forum dialog antar umat beragama . ( Zaini, 121 : 1990 ) Belum lagi inisiatif dan prakarsa penyelenggaran dialog tersebut merambah dari instansi departemen atau kantor wilayah organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan yang tersebar luas di tanah air, masyarakat mulai mempertanyakan efektifitas dan kegunaan dialog antar umat beragama yang dilakukan selama ini. Ada paradoks dan keganjilan disini. Masyarakat pemerhati kehidupan sosial-keagaam ditanah air bertanya-tanya, mngapa semakin banyak dialog antar umat beragama diselenggrakan, setidaknya setelah tahun 1970-an, semakin banyak pula konflik antar umat beragama dan warga Indonesia pada umumnya.
Kerusuahan di tanah air, sejak dari Pekalongan ( 1995 ), Tasikmalaya (1996 ), Rengasdengklok ( 1997 ), Sanggau Ledo, Kalimantan Barat ( 1996 1997) sampai yang terjadi di Ambon, Maluku dan Poso ( 1999-2007 ), menunjukan bahwa rupanya dialog antar umat beragama hanya efektif dan berguna untuk elit pemimpin agama, tetapi belum dapat menyentuh lapis bawah dan akar rumpu umat. Bahkan ketika para elit agama, elit penguasa, elit pemimpin masyarakat, elit politik menganalisa akar permasalahan dan sumber konflik tersebut, mereka hampir semuanya sepakat untuk menyebut bahwa faktor ekonomi ( kesenjangan ekonomi dan sosial ) sebagai biang keladi dan faktor utama pemicu kerusuhan sosial yang terjadi di tanah air dan sangat sedikit sekali mencurigai agama sebagai faktor yang cukup signifikan dalam memicu kerusuhan sosial yang berbau SARA.( Tomagola, 6 : 1999 ). Ada keseganan tersendiri untuk meyebut agama sebagai salah satu faktor penyebab konflik dan kerusuhan di tanah air. Karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat relegius.
Dengan demikian, tertutuplah sudah usaha-usaha untuk mempertanyakan ulang bagaimana sesungguhnya praktik pengajaran dan pendidikan agama, baik yang menyangkut materi, maupun methodology di sekolah-sekolah, di seminari-seminari, di pesantren-pesantren dan di masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memperlunak kekakuan dan mencairkan kebekuan pemikiran keagamaan dan ketegamangan hubungan sosial-keagamaan dari masing-masing kelompok penganut agama belum diangap terlalu penting untuk diangkat kepermukaan dan tidak perlu didiskusikan secara terbuka.
Diakui bahwa kesenjangan ekonomi menjadi salah satu faktor utama pemicu terjadinya kerusuhan dan keresahan sosial di tanah air, tetapi dalam antisipasi konflik SARA dicoba dilihat kemungkinan adanya andil yang diberikan oleh agama sebagai salah satu faktor yang cukup potensial dan signifikan dalam menyulut bahkan memelihara dan melestarikan sunber konflik yang bernuansa SARA.
Aspek Norma dan Historis Keberagamaan Manusia
Mempermudah alur analisis, perlu dibedakan terlebih dahulu antara wilayah agama yang bersifat normatif dan Historis meskipun dalam praktek hidup sehari-hari, pencampuradukan antara keduanya tidak dapat dihindarkan. Dalam praktek dilapangan, campuraduk antara keduanya lebih umum terjadi daripada keterpisahan antara keduanya. Campuraduk dan tumpang tindih antara keduanya menjadikan fenomena agama menjadi unik dan komplek. Disatu sisi, fenomena keberagamaan terkait dengan unsur sakralitas transendental, namun disisi lain, ia juga terkait langsung dengan fenomena budaya dan sosial.
Konsekwensinya, memahami fenomena agama dibutuhkan peralatan methodologis yang khusus. Disamping orang perlu mengenal pendekatan psikologis dan filosofis eksistensial, ia juga dituntut untuk mampu menghargai dan sekaligus menggunakan pendekatan dan metdhologi yang bisa digunakan dalam bidang-bidang budaya dan sosial.
Berbeda dari fenomena budaya dan sosial yang biasa, kenyamanan antara keduanya menjadikan fenomena agama, menjadi sangat pelik dan komplek. Dalam pengalaman mengajar di Institut Agama Islam Negeri ( IAIN /STAIN/UIN ) pada level S1, S2 dan S3, amat sulit menjelaskan kepada mahasiswa bahwa fenomena agama dalam satu dan lain hal adalah merupakan fenomena budaya dan sosial. Jika dosen agama berani memasuki wilayah pendekatan terhadap fenomena keberagamaan seperti tu, belum-belum sang dosen sudah tertuduh sebagai sang reduksionis.
Oleh karena itu secara relatif pendekatan budaya dan sosial terhadap fenomena keberagamaan manusia kurang begitu di kenal di PTAIN. Mata kuliah methode study Islam pada jenjang S1 dan pendekatan dalam pengkajian Islam pada jenjang S2 di maksudkan untuk mengisi kekurangan yang telah lama dirasakan, khususnya di PTAIN dan umat Islam pada umumnya.
Norma dan aturan agama yang diklaim sebagai yang bersumber dari Ilahi, yang suci, yang samawi, yang sakral, yang ultimate menjadikan agama mempunyai ciri yang spesifik dan unik, sekaligus membedakannya dari jenis-jenis pengalaman budaya dan sosial keagamaan yang lain.( Dale, 50: 2001 ). Dimungkinkannya trut and claim ( klaim kebenaran ) yang biasa terjadi pada penganut agama-agama, sebagian bersumber dari apa yang disebut suci ini. Sampai disini barangkali tidak ada masalah. Namun ketika disebut bersumber dari yang ilahi dan diungkapkan dengan bahasa agama tertentu maka serta merta campur tangan budaya dan sosial tidak dapat dihindarkan sama sekali.
Dalam praktek kehidupan sehari-hari dalam bidang kehidupan apapun, orang atau masyarakat akan mudah bersepakat bahwa dalam bidang yang bersifat normatif, belum tentu cocok dengan wilayah praksis yang bersifat historis-empiris. Hal tersebut dapat dimaklumi karena keterlibatan faktor kepentingan baik kepentingan kelompok, pribadi, golongan, ekonomi, suku, etnis, sosial, budaya, pengusaha, pertahanan negara dan pemerintah. Tanpa dukungan data dari wilayah histories-empiris, maka norma hanyalah sebuah cita-cita, angan-angan sosial, gagasan, ide-ide bahkan mungkin hanya sampai pada batas wishful thinking yang belum tentu sepenuhnya dapat direalisasikan dalam praktek hidup keseharian.
Wajah Pendidikan Agama di Era Multikulturalisme
Pendidikan agama yang diajarkan mulai tingkat yang paling rendah ( TK /PAUD) sampai perguruan tinggi tidak luput dari telaah teoritik baik dari aspek normatif maupun historisnya. Maka amat menarik untuk mengkaji ulang dan mencermati paradigma konsep pendidikan agama yang ditawarkan oleh kurikulum, silabi, literatur dan pengajarnya di lapangan dalam era multikulturalisme. Lebih-lebih jika upaya demikian dikaitkan dengan pencarian sebagaian sumber atau akar-akar konflik dan kerusuhan dalam masyarakat plural.
Dialog antar umat beragama secara terbatas hanya melibatkan tokoh-tokoh di elit organisasi keagamaan, fungsionaris yang berwenang dalam lembaga-lembaga keagamaan, tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap terpandang. Namun jarang sekali forum-forum dialog ini melibatkan guru-guru agama. Mereka sebagai ujung tombak pendidikan agama dari TK sampai perguruan tinggi nyaris tidak pernah tersentuh dari gelombang pemikiran dan diskursus pemikiran kegamaan diseputar isu pluralisme dan dialog antar umat beragama selama hampir 30 tahun terakhir.
Dengan demikian dalam mindset ( pemikiran ) mereka pada umumnya masih terpanggil untuk mengajarkan agama dengan materi, cara dan methode yang sama dengan asumsi dasar keyakinan dan pra anggapan-anggapan mereka bahwa anak didik masyarakat dan umat diluar sekolah seolah-olah hidup dalam komunitas yang homogen dan bukan heterogen secara keagamaan.
Jika saja mereka memperoleh informasi yang akurat tentang kompleknya kehidupan beragam dalam era plurlitas dan memberikan alternatif-alternatif pemecahan yang menyejukan, lebih-lebih jika mereka mampu mengemas ulang pesan-pesan nilai-nilai agama yang mereka peluk di era pluralitas, maka anak didik dari sejak dini sudah dapat diantarkan untuk dapat memahami ( bukan menegasikan perbedaan dan menolaknya ), menghargai dan menghormati kepercayaan dan agama yang dianut atau dipeluk orang lain ( bukan membecinya dan memusuhinya ). Dengan demikian, pada saatnya mereka dapat mengambil sikap dan menghadapi realitas pluralitas agama, budaya, suku, etnis, dan golongan secara lebih arif, matang dan dewasa.( Depag, 11 : 2001 ).
Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diangkat dan didiskusikan lebih lanjut tentang sebuah pertanyaan mendasar untuk dijawab terlebih dahulu oleh para konseptor atau para praktisi pendidikan agama yang bergumul dengan realitas keseharian kehidupan anak didik didalam dan diluar bangku sekolah dan kuliah adalah apakah pendidikan agama baik pendidikan agama Islam, Katholik, Budha, Konghucu dan lainnya telah cukup memberi bekal kepada anak didik ketika mereka harus berhadapan dan menghadapi realitas aktual dan kongkrit tentang keberanekaragaman yang dianut oleh anggota masyarakat baik nasional ataupun internasional?.
Jika memang sudah, bagaimana bnetuk materi dan methodology yang digunakan ?sudah adakah tema atau subtema bahasan yang menyentuh persoalan pluralitas agama secara langsung dalam satu paket pendidikan agama yang biasa mereka ajarkan kepada anak didik. Jika memang sudah ada, bagaimana seorang guru atau dosen menyampaikan dan membawakannya ? sudah barang tentu hal ini berkaitan dengan methodology pengajaran.
Bahkan yang serius lagi, apakah tema-tema tersebut pernah didiskusikan secara sadar dalam lingkungan perguruan tinggi sebagai tempat penggodokan calon-calon guru agama dan dosen-dosen agama hingga sekarang memang belum secara sadar dan terencana dibekali oleh isu-isu aktual, solidaritas hidup bersama secara kongkrit. Dapat dibayangkan jika masing-masing calon guru agama beranggapan demikian, maka mustahil rasanya para guru dan dosen agama akan mengenal dan akrab dengan isu pluralitas agama yang dihadapi oleh anak didik secara kongkrit dalam kehidupan diluar bangku sekolah ataupun kuliah.
Sudah lumrah terjadi bahwa materi dan methodology pendidikan agama terlalu lambat perkembangannya jika dibandingkan dengan laju perkembangan yang terjadi di luar, tren atau kecenderungan untuk mempertahanakan al-qadim (konsep-konsep pendidikan agama yang lama dan dianggap telah teruji ) yang dianggap dan dipercayai pasti jauh lebih baik (al-aslah ) dalam pendidikan agama, lebih dominan untuk mengambil konsep pendidikan yang al-jadid ( baru ) yang lebih baik dan sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman.
Oleh karena itu, dapat difahami jika sikap guru-guru agama dan anak didik dalam menghadapi pluralitas komunitas dan penganut-penganut agama diluar yang biasa mereka kenal dan memiliki nyaris tidak beruabah. Isu-kafir mengkafirkan, antar kelompok pengikut agama, tuduhan tidak selamat jika mneganut diluar agama yang mereka anut, saling murtad memurtadkan keberadaan orang lain sebagai ancaman masih sering dijumpai dalam praktek pendidikan agama manapun secara terang-terangan maupun secara halus yang pada akhirnya emosi sosial dan kelompok keagamaan mudah disulut dan dibakar oleh provokator yang mempunyai kepentingan politik, sosial, ekonomi dan budaya.
Materi buku-buku dasar agama, jarang menyentuh isu pluralitas agama. Materi pluralitas agama dan kemajemukan keberagamaan hanya diperoleh anak didik lewat pendidikan kewarganegaraan dan moral Pancasila, namun amat jarang yang masuk dalam satu komponen yang utuh dalam materi pendidikan agama.
Rekontruksi Pendidikan Agama
Agak sulit membeyangkan bekal apa yang dapat diberikan dan diperoleh anak didik entang bagaimana secara sosial dan secara agamis mereka dapat mengatasi persoalan pluralitas keagamaan dalam kehidupan yang nyata di tengah-tengah masyarakat. ( P3PK, 19: 1997 ).
Pendidikan dan pengajaran agama pada umumnya masih lebih menekankan sisi keselamatan individu dan kelompoknya sendiri, dengan mengesampingkan keselamatan yang dimiliki dan didambakan oleh orang lain diluar dirinya dan kelompoknya sendiri.
Visi dan misi pendidikan agama tampak sekali diwarnai dan didominasi oleh asumsi dasar paradigma klasik-skolastik dari para konseptor dan perancangnya yang terlalu menggarisbawahi keyakinan dan anggapan bahwa keselamatan sosial dan keselamatan kelompok amat tergantung pada keselamatan individual, dengan kata lain bahwa keselamatan individual bagaimanapun jauh lebih pokok dan lebih utama daripada keselamatan sosial. Dalam arti, jika individu-individu dalam masyarakat bertingkah laku dengan baik dan bermoral secara agamis, maka secara otomatis kehidupan kelompok sosial dan kolektif juga akan berlaku baik dan bermoral agamis. Paradigma psikologi individual kependidikan lebih dominant daripada psikologi sosial, asumsi demikian terlalu menyederhanakan persoalan dalam realitas kehidupan kelompok.
Cara penanganan kasus-kasus yang dialami oleh individu-individu sangat berbeda dari cara penanganan kasus-kasus yang dialami oleh kelompok. Kemarahan masa yang berkerumun, fenomena adanya provokator, keresahan sosial, penyebaran isu negatif dan tidak bertanggungjawab, kekerasan massa secara kolektif tidak dapat dijelaskan, diselesaikan dan diantisipasi lewat pengajaran agama yang hanya melalui penekanan pada keselamatan individu secara eksklusif.
Konsep kerukunan umat beragama yang hanya dilandaskan pada jaminan keselamatan individual dengan tolak ukur kekuatan aqidah, iman atau credo tertentu masih harus diuji dilapangan, jika individu individu tersebut mengelompok, berkerumun dan berorganisasi dengan berbagai kepentingan yang melekat didalamnya yang sering kali diatasnamakan agama untuk menarik emosi dan dukungan yang penuh penganut agama tersebut, maka harus diklarifikasikan dengan bentuk kesepakatan-kesepatan yang lebih mengedepankan kepentingan sosial bukan kepentingan agama.
Dalam konsep agree in disagreement masih tampak corak pendekatan teologi yang cukup menonjol dan sangat kental dengan nilai-nilai agama masing-masing, lantaran disagreement masih sempat ditonjolkan, sedang komponen agree-nya bisa saja cepat tertindih oleh disagrementnya. Sedangkan state of mind, mentalitas dan mentalitas dan cara berfikir serta cara bertindak yang tersembunyi dibalik kata kunci kontrak sosial adalah sebuah asumsi dan keyakinan bahwa kita semua sejak semula memang berbeda dalam banyak hal, lebih-lebih dalam bidang aqidah, akan tetapi demi menjaga keharmonisan, keselamatn dan kepentingan kehidupan bersama dan kelompok ( sosial survival ) mau tidak mau kita harus rela untuk menjalin corporation ( kerjasama ) dalam bentuk kontrak sosial antara sesama kelompok dan warga masyarakat yang memang sejak semula berbeda ditinjau dari sudut pandang apapun.
Penutup
Pertanyaan mendasar dapatkah seorang manager sosial, praktisi dan komponen yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan pendidikan agama di era multikultiralisme dapat menyusun dan mengajukan konsep baru yang bernuansa reformatif untuk pembenahan muatan materi, silabi, kurikulum dan litertatur dalam bidang pendidikan agama di sekolah-sekolah dan bangku kuliah?
Upaya-upaya yang bernuanas reformatif dan rekontruktif terhadap pendidikan agama dan pendidikan sosial keagamaan era multikulturalisme sangatlah ditunggu-tunggu oleh amsyarakat luas.
Upaya-upaya yang bernuansa reformatif dan rekontruktif yang mempunyai corak dan titik tekan pada tataran iman, aqidah dan identitas diri dan kelompoknya diganti dengan titik tekan memperteguh dan memperkokoh kepentingan dan solidaritas sosial kemasyarakatan untuk menghadapi tantangan, benturan dan tuntutan era globalisasi, kompetisi, dan pluralisme budaya, agama, suku, etnik dan ras.
Rupanya ijtihad dalam bidang pendidikan dalam bidang yang terkait langsung dengan pendidikan agama untuk keIslaman dan keindonesiaan saat sekarang ini lebih jauh diperlukan dan mendesak sifatnya daripada ijtihad-ijtihad dalam bidang hokum yang biasa dikonsepkan, difahami, dikonotasikan dan dijalankan selama ini.
Daftar Pustaka
Dale Cannon, 2001. Six Way Of Being Relegious, Belmont, Wadworst Company
Departemen Agama RI, 2001 .Alquran dan Terjemahannya, Jakarta, DEPAG RI
P3PK, 1997. Keimanan Beragama dan Peranan Pendidikan Agama, Yogyakarta : UGM-Depag RI,
Tomagola Thamrin Amal, 1999. Dibakar Sumbu Agama, Jakarta : Republika
Zaini Muhtarom dkk, 1999. Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia (Beberapa Permasalahan ), Jakarta : INIS.
skip to main |
skip to sidebar
Silahkan Kirim Artikel Anda Kpd Kami bisa melalui Email darussholah@gmail.com
WebLink
Label
- Kata Mutiara (6)
- Keagamaan (52)
- Khutbah Jum'at (15)
- Pendiri Darus Sholah (8)
- Terjemahan Kitab Aswaja (1)
- Tokoh (14)
- Wawasan (3)
Artikel Populer
- KHUTBAH JUM’AT BULAN SYAWAL
- KHUTBAH JUM’AT BULAN SHAFAR
- KHUTBAH JUM’AT BULAN MUHARRAM
- KHUTBAH JUM’AT BULAN DZULQO’DAH
- APLIKASI METODE DISCOVERY LEARNING DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMECAHKAN MASALAH, MOTIVASI BELAJAR DAN DAYA INGAT SISWA
- KHUTBAH JUM’AT BULAN RAJAB
- KEMU'JIZATAN AL-QUR'AN DARI SEGI BAHASA & ISYARAT ILMIYAH
Buku Tamu
Copyright © 2011 Darus Sholah Jember | Powered by Blogger


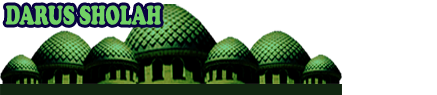
 21.50
21.50
 darussholah
darussholah

 Posted in:
Posted in:
0 komentar:
Posting Komentar