Gerakan Keislaman Modernis dan Tradisionalis di Indonesia
Oleh: M. Syamsudini, M.Ag
Abstrak
Dalam abad ke-21 ini, membincangkan wacana dikotomis Islam tradisional-Islam modernis mungkin tidak lagi dirasakan sebagai suatu perkara yang relevan untuk dikaitkan dengan gerakan-gerakan keagamaan (Islam). Akan berbeda jika perbincangan itu terfokus pada gerakan-gerakan keagamaan yang dilakukan kaum muslimin pada abad 20 dimana perbedaan antara dua kelompok tersebut masih sangatlah tajam
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) merupakan dua organisasi muslim terbesar yang ada di Indonesia. Pengaruh dari kedua organisasi ini amat terasa ditengah masyarakat, meski berbeda massanya. Dakwah bil lisan maupun bil hal yang menjadi ciri khas kedua ormas keagamaan ini sudah sejak lahirnya diketahui masyarakat, bukan saja didalam negeri, tetapi juga di luar negeri.
Tulisan ini akan mencoba memetakan tipologi dari kedua organisasi tersebut, dimana Nahdlatul Ulama menjadi wakil contoh dari gerakan Islam Tradisionalis dan Muhammadiyah yang selama ini dikenal sebagai pejuang gerakan Islam Modernis. Di akhir tulisan akan membincangkan gerakan Post-Tradisionalis yang mencoba untuk memperkecil jurang keterpisahan dari kedua gerakan tersebut
Key Word : Islam Tradisionalis, Islam Modern dan Post Tradisionalis
A. Pendahuluan
Pada awal abad ke 20 , di Indonesia khususnya di Sumatera dan Jawa, bergema seruan untuk “kembali kepada al-Qur’an dan Hadits” yang dipelopori oleh kaum modernis. Sambil menyuarakan seruan itu, kaum modernis juga mengecam praktek pelaksanaan ritual adat yang berlaku di masyarakat yang di kategorikan termasuk TBC (Tahayul, Bid’ah dan Churafat).
Tak dapat diragukan lagi bahwa lahirnya gerakan pembaharuan Islam di Indonesia itu memperoleh inspirasinya terutama dari gerakan purifikasi Muhammad Ibnu Abdul Wahab dan idea-idea pembaharuan yang dicetuskan oleh Sayyid Jamaludin al-Afghani (1839-1879) dan Muhammad Abduh (1849-1905)
Pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh yang masa itu tertuang dalam pelbagai majalah seperti al-‘Urwatul Wutsqa, as-Siyasah, Thamarat al-Funun dan al-Qisthas al-Mustaqim dengan gencar diteruskan oleh KH. Ahmad Dahlan sang Pendiri Muhammadiyah melalui majalah yang bernama al-Manar. Dari fenomena tersebut, boleh dikatakan hubungan antara Ahmad Dahlan dengan Muhammad Abduh terjalin sedemikian rupa karena adanya persamaan cita-cita, yakni cita-cita pembaharuan.
Ahmad Dahlan di lahirkan pada tahun 1868 di Kauman Yogyakarta dengan nama kecilnya Mohammad Darwis, ayah beliau KH. Abu Bakar adalah Khatib Besar Masjid Kasultanan Yogyakarta, sementara sang ibu adalah putri dari Haji Ibrahim bin H. Hasan seorang penghulu yang mengabdi untuk keraton Yogyakarta
Metod pemahaman dan pengamalan Islam Ahmad Dahlan adalah rasional-fungsional. Rasional dalam pengertian menelaah sumber utama ajaran Islam dengan kebebasan ajaran akal pikiran dan kejernihan akal nurani. Fungsional bermakna kelanjutan dan tuntutan hasil pemahaman tersebut adalah aksi sosial, iatu melakukan perbaikan kehidupan masyarakat
Untuk melaksanakan ide-ide pembaharuannya, pada 18hb November 1912 yang bertepatan dengan 8hb Zul Hijjah 1330, Ahmad Dahlan menubuhkan organisasi Muhammadiyah dengan motifasi pertama, menjawap persoalan kemasyarakatan seperti kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan yang dijadikan agenda tersendiri dalam pengentasan sosial, dan kedua, Persoalan pemahaman agama yang semakin terreduksi dengan tradisi-tradisi lokal yang kemudian hal inipun dijadikan agenda yang tersendiri pula yang dikemas dalam konsep tajdid (pembaharuan) sekaligus tanzih (purifikasi).
Menurut Prof. Dr. A. Mukti Ali, salah satu ciri gerakan yang bernuansa Islam baru dapat disebut “modern” manakala gerakan keagamaan tersebut menggunakan metode “organisasi” sehingga dengan demikian Muhammadiyah dapat dikatakan sebagai satu gerakan keagamaan Islam yang modern.
Pada tahun 1968, Nurcholis Majid merumuskan modernisasi sebagai rasionalisasi. Pengertian yang mudah mengenai modernisasi ialah pengertian yang identik atau hampir identik dengan pengertian rasionalisasi. Dan itu berarti proses perombakan pola pikir dan tata kerja baru yang rasional. Kegunaannya ialah untuk memperoleh daya guna yang maksimum. Jadi, sesuatu yang dapat disebut modern adalah jika ia bersifat rasional, ilmiah dan bersesuaian dengan hukum-hukum yang berlaku dalam alam
Setidaknya, ada 3 faktor yang menjadi pemicu KH. Ahmad Dahlan menubuhkan Muhammadiyah, yakni (1) Ajaran Islam tidak dilaksanakan secara murni bersumberkan al-Qur-‘an dan Hadith akan tetapi bercampur syirik, bid’ah dan khurafat, (2). Lembaga-lembaga Islam tidak lagi dapat memenuhi tuntutan zaman kerana terlalu menutup diri dari pengaruh luaran (akibat adanya budaya taklid) dan, (3). Keadaan umat yang sangat menyedihkan di bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya sebagai akibat penjajahan.
Dengan demikian, muncul dua pandangan yang berkaitan dengan penubuhan Muhammadiyah, pandangan pertama menyatakan bahwa kelahiran Muhammadiyah dipicu oleh tersebarnya gagasan-gagasan pembaharuan Islam dari Timur Tengah ke Indonesia pada tahun-tahun pertama kurun ke-20. Pandangan kedua, menyatakan bahwa berdirinya Muhammadiyah adalah sebagai respon internal terhadap pertentangan ideologis yang telah berlangsung lama alam masyarakat Jawa, sehingga Islam bercampuir dengan perkara-perkara sinkretism dalam tradisi dan kebudayaan masyarakat Jawa
Menurut Amien Rais, tradisi yang sudah demikian kuat turun-temurun pada hakikatnya juga dapat memenjarakan banyak orang. Memang tidak semua tradisi bernilai buruk. Banyak sekali tradisi yang bernilai baik. Akan tetapi tradisi yang tidak rasional, yang bercanggah dengan akal sehat, yang terus saja diikuti, pada dasarnya juga dapat menjadi penjara.
B. Gerakan Modernisasi Muhammadiyah
Tajdid gaya Muhammadiyah sebenarnya hanya berkisar pada gerakan purifikasi (pemurnian) keagamaan dan modernisasi pada aras praksis sosial. Untuk yang pertama, Muhammadiyah melancarkan kritik terhadap praktik semiritual keagamaan yang biasa disebut bid’ah, khurafat, dan tahayyul. Mesti diakui ada kepentingan pembaruan yang bersifat purifikatif, yaitu pemurnian keyakinan akidah dari hal-hal yang dianggap mengotori. Inilah yang sering terjadi melalui proses sejarah, sebagai akibat pertemuan Islam dengan kebudayaan lokal .
Dalam banyak hal, langkah ini penting, terutama untuk mengurangi "meluasnya" hal-hal yang tidak rasional dalam agama. Kerana, yang disebut tahayyul, bid’ah dan khurafat sebenarnya adalah unsur yang tak rasional dalam agama, yang tidak secara mudah dicerna oleh nalar.
Purifikasi gaya Muhammadiyah memang tidak seradikal gerakan Wahabi di Arab Saudi, misalnya, dengan membongkar kuburan yang dianggap keramat. Mungkin karena Muhammadiyah lahir di Jawa sehingga gayanya agak lain. Muhammadiyah lebih toleran sesuai langgam kejawaannya. Meski demikian, tetap ada unsur budaya (Islam) yang dipangkas sehingga mengebiri perkembangan seni-budaya Islam di Indonesia.
Dalam konteks aras tajdid kedua, yakni modernisasi, Muhammadiyah mampu mengadopsi dan mengadaptasi wacana dan sistem pendidikan serta lembaga moden model Barat Kristen ke dalam tradisi Islam. Sisi penting ini pada gilirannya, melahirkan berbagai amal-usaha sebagai konsekuensi logis dari rasionalisasi dan obyektivikasi keimanan yang rasional. Jadi, keyakinan teologis inilah yang melahirkan aktivisme sosial sekaligus intelektualisme baru sebagai tuntutan untuk memahami terus-menerus doktrin Islam, Al Quran dan Sunah Nabi.
Kegiatan Muhammadiyah dalam aspek pendidikan merupakan upaya untuk mempertemukan sistem pendidikan pesantren yang tradisional dengan sistem pendidikan barat yang sekular. Sejajar dengan tujuan ini, Muhammadiyah telah memperkemaskan kurikulum pendidikan Islam dan memasukkannya kedalam sekolah-sekolah umum dan sebaliknya, memasukkan pengetahuan sekular ke dalam sekolah agama, dengan kata lain, Muhammadiyah menawarkan suatu sistem pendidikan yang bersepadu.
Yang tak kalah pentingnya adalah gerakan Muhammadiyah dalam bidang sosial kemasyarakatan yakni dengan mendirikan panti asuhan bagi anak yatim, pembinaan klinik, rumah sakit dan lain sebagainya yang kesemuanya tergabung dalam sebuah lembaga yang disebut “Penolong Keselamatan Umum” (PKU)
Adanya slogan “kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah” yang diwar-warkan oleh kelompok modernis sesungguhnya adalah berdasarkan penilaian mereka bahwa telah terjadi penurunan kualitas akidah karena telah terjejas dengan hal-hal seperti bid’ah, khurafat dan takhayyul. Pada sisi lain, kualitas aqidah adalah persoalan yang sangat asasi sifatnya, jadi dapat kita bayangkan apabila asas dari sesuatu itu sudah tak benar, maka keseluruhan nilai yang dibina diatasnya pun menjadi kacau bilau.
Jika kita cermati lebih jauh, gerakan-gerakan pembaharuan Islam yang berlaku pada kurun ke-20 mempunyai asas yakni yang pertama gerakan-gerakan itu datang dari masyarakat Islam sendiri, jadi bukan karena sentuhan dan desakan Barat seperti yang difahami oleh sebahagian orang, kedua, gerakan-gerakan itu melakukan kritik terhadap praktek sufisme yang cenderung menjauhi tugas-tugas manusia muslim dalam pergumulan sosial di dunia riil, sufisme dianggap sebagai penyebab terbesar mengapa masyarakat Islam menjadi mandek dan kehilangan kreatifitasnya, ketiga, hampir semua gerakan pembaharuan tersebut menekankan mutlak perlunya rekonstruksi sosio-moral dan sosio-etis masyarakat Islam agar sesuai dengan --atau setidaknya mendekati-- Islam Ideal, Islam sejarah yakni Islam dalam praktek harus kembali ditransformasikan menjadi Islam Ideal, keempat, semua gerakan pembaharuan itu mengobarkan semangat ijtihad, yaitu menggunakan kemampuan akal pikiran secara maksimal untuk memcahkan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat Islam dengan referensi al-Qur’an dan Sunnah dan kelima, gerakan-gerakan pemabaharuan itu juga menekankan pentingnya jihad yakni pengerahan total segenap daya dan upaya untuk merealisasikan cita-cita pembaharuan.
B. Gerakan Tradisionalis Nahdlatul Ulama’
Gencarnya gerakan modenisasi yang berjalan di dalam negeri (Indonesia) mahupun dalam skup internasional yang dilancarkan oleh kaum pembaharu, dimana mereka mengecam sufism, melarang ziarah kubur dan semua praktik-praktik keagamaan yang bermuatan budaya lokal akhirnya memunculkan reaksi antisipatif dari ulama-ulama aliran tradisionalis. Dipimpin oleh KH. Hasyim Asy’ari, Pendiri dan Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur, para ulamak tersebut menubuhkan Jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya pada 31hb Januari 1926 bertepatan dengan 16hb Rajab 1344H.
KH. Hasyim Asy’ari adalah seorang kyai paling besar dan paling terkenal seluruh Indonesia pada masa separuh pertama kurun ke-20, selama masa hidupnya beliau menjadi pusat pertalian yang menghubungkan para kyai utama seluruh pulau Jawa.
Pada hari itu diadakan mensyuarat yang menghasilkan 2 keputusan penting, yakni pertama, mengirim utusan ulamak Indonesia ke Kongres Dunia Islam di Mekkah dengan misi memperjuangkan hukum-hukum ibadah menurut mazhab empat, dan kedua, menubuhkan Jam’iyah NU sebagaimana tadi telah disebutkan.
Zamakhsari Dhofier memberikan pengertian bahwa Islam Tradisional sebagai kelompok muslim yang masih terikat kuat dengan pikiran-pikiran para ulamak ahli fiqh (hukum Islam), hadits, tafsir, tauhid (teologi Islam) dan tasawuf yang hidup antara kurun ke 17M sampai dengan kurun ke 13 M. Dengan demikian NU sangatlah beralasan untuk dikategorikan sebagai kelompok tradisionalis, apalagi secara lebih spesifik mereka mengklaim keutamaan untuk berpegang teguh kepada salah satu madzhab empat dalam bidang fiqh, mengikuti faham aliran Asy’ari atau al-Maturidi dalam teologi dan imam al-Ghazali dan Junaidi al-Baghdadiy dalam bidang sufisme.
Memahami NU sebagai organisasi keagamaan memang tidaklah cukup setakat hanya mengkaji dari sudut formal semenjak ianya ditubuhkan, akan tetapi jauh sebelum masa itu, telahpun ada komunitas yang terikat kuat secara emosi maupun spiritual yang memiliki karakteristik tersendiri, yakni komunitas para kyai/ulamak. Ditubuhkannya NU sebagai perkumpulan tiada lain untuk memanage potensi dan peran para kyai tersebut dalam satu perkumpulan untuk ditingkatkan dan dikembangkan lebih luas lagi, dan salah satu motivasinya adalah untuk mempertahankan paham ahli sunnah wal-jama’ah. Dengan kata lain, sebagai reaksi dari gerakan kaum pembaharu yang menyerukan untuk “kembali kepada al-Qur’an dan Sunnnah”.
Pada masa itu, walaupun perselisihan antara kaum tradisionalis dengan kaum pembaharu pada intinya hanyalah dalam medan parsial (furu’iyah) akan tetapi konflik itu berjalan cukup lama dan terjadi sangat kuatnya. Bahkan seringkali diadakan perdebatan yang memang disiapkan untuk disaksikan oleh khalayak ramai, yang dikenal dengan istilah “Openbaar Debat” atau “Openbaar Vergadering”. Seiring berjalannya waktu, perdebatan dan pertentangan itupun tak lagi muncul ke permukaan meskipun perbedaan cara pandang masih lagi tetap kekal sehingga kini.
Kalangan tradisionalis menyebut diri mereka sebagai ahlus sunnah wal jama’ah (atau seringkali disingkat menjadi Aswaja). Istilah ini secara tegas menyingkirkan para rasionalis-modernis yang lebih mengutamakan penggunaan nalar daripada sunnah nabi. Mereka bertahan dengan sikap taqlid samada dalam bidang fiqh yang menurut mereka adalah ratu dari ilmu pengetahuan kerana merupakan petunjuk atas setiap prilaku, penjelas apa yang boleh dan tidak boleh. Prinsip taqlid itupun berlaku dalam ilmu keagamaan yang lain seperti dalam doktrinasi (aqidah) ataupun mistisisme (tasawuf).
Bertahannya kaum tradisionalis dengan prinsip taqlid berakar dari pandangan sejarah yang pesimistik yakni kian berjaraknya masa kini dengan masa Nabi, maka pengetahuan dan kesalehan umat Islam kian berkurang. Ulamak sekarang ini diyakini semata-mata menjadi bayangan para ulama besar dimasa sebelumnya, dan barang siapa saja yang mengaku mampu melakukan ijtihad secara individu dan mandiri dianggap sebagai kesombongan yang tidak sepatutnya dilakukan.
C. Pesantren Sebagai Tempat Kaderisasi Kelompok Tradisionalis
Pondok pesantren adalah institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia, meskipun belum pernah ada catatan pasti yang menerangkan awal keberadaannya, akan tetapi pesantren telah dikenal sejak zaman walisongo manakala menyebarkan agama Islam di Jawa.
Pesantren yang menjadi basis massa dan pusat pengkaderan kaum tradisionalis memang telah berakar kuat ditengah masyarakat dan merupakan institusi lembaga pendidikan yang tertua di nusantara . Pola-pola tradisionalism dengan mudah kita baca berlaku di pesantren --terutamanya pesantren salaf-- baik dalam sistem pengajaran, materi yang diajarkan ataupun pola hidup yang cuba untuk dikembangkan.
Dalam pesantren salaf (menganut sistem tradisional) kedudukan guru/kyai adalah sumber ilmu yang sangat vital. Tingkat penghormatan terhadapnya boleh dibilang sangat mengagumkan, dimana mereka berpedoman pada kitab Ta’limu al-Muta’alim li Thariqi al-Ilmiy karangan Syekh Az-Zarnujiy yang ditulis pada kurun ke-14, salah satu kaedah dalam kitab tersebut menyebutkan, menghormati guru adalah dengan cara diantaranya jangan berjalan didepannya, duduk di tempat duduknya, jangan mulai mengajak bicara kecuali diperkenankannya, berbicara macam-macam, menanyakan hal yang membosankan. Jangan mengetuk pintu rumahnya, cukuplah sabar menanti diluar sehingga beliau sendiri keluar dari rumah. Hormati pula anak serta semua orang yang menjadi ahli keluarganya.
Abdurrahman Wahid memberikan argumentasi bahwa ketaatan santri kepada kyai/ulamak lebih disebabkan kerana mengharapkan barakah (grace) sebagaimana dipahami dalam konsep sufism. Kerangka sistem nilai tersebut dipercaya dapat mempermudah bagi para santri dalam penguasaan ilmu-ilmu agama yang benar (right religious science)
Keikhlasan, kealiman, istiqomah dan tawadlu’ (rendah diri) dan ketelatenan sang kyai adalah modal utama yang dapat memproduk santri yang allamah dan berakhlak mulia sekaligus sebagai bukti nyata kesuksesan pesantren dalam mencetak generasi penerus ulama, zu’ama dan fuqoha. Di samping itu dalam proses pembelajarannya santri dituntut untuk menjauhi maksiat dan meninggalkan segala larangan kyai, dibarengi juga dengan tindak laku prihatin, seperti berpuasa sunnah, menghindari makan yang berasal dari ikan dan daging haiwan, memperbanyak zikir dan ibadah2 lain, dari situ diharapkan ilmu yang didapatkan juga di imbangi dengan mantapnya jiwa yang dihasilkan dari olah batin tersebut.
Dari fenomena tersebut, kita dapatkan nilai positif seperti terciptanya mekanisme kontrol atau sistem pengawasan yang berjalan selama proses pembelajaran sehingga pendidikan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, akan tetapi disisi lain juga memunculkan faktor negatif yakni sikap kebergantungan (paternalistik) dan bahkan dalam kondisi yang ekstrem kemungkinan dapat terjadi pengkultusan individu terhadap kyai.
Kewibawaan dan pengaruh kyai yang sudah sedemikian membudaya tersebut tercermin secara formal-organisatoris pada struktur kepengurusan jam’iyah NU, dimana Lembaga Syuriah adalah lembaga tertinggi atau Dewan Legislatif yang selalunya diwakili oleh figur-figur ulamak besar pada zamannya. Lembaga syuriah itu memiliki posisi yang superior serta memiliki fungsi pengawasan terhadap Lembaga Tanfidziyah (Dewan eksekutif) yang merupakan campuran antara ulamak dan warga biasa.
Dalam konteks yang lain, pesantren sebagai lembaga pendidikan mempunyai watak utama iaitu sebagai lembaga pendidikan yang memiliki ciri-ciri khas. Karena, pesantren memiliki tradisi keilmuan yang berbeda dengan tradisi keilmuan lembaga-lembaga pendidikan lainnya, seperti madrasah atau sekolah. Salah satu ciri utama pesantren sebagai pembeza dengan lembaga pendidikan lain, adalah pengajaran kitab-kitab salaf yang secara introdusir dengan sebutan kitab kuning, kitab-kitab Islam klasik yang ditulis dalam bahasa Arab baik yang ditulis oleh para tokoh muslim Arab maupun para pemikir muslim Indonesia. Disebut kitab kuning karena memang kitab-kitab tersebut dicetak diatas kertas berwarna kuning, meskipun sudah banyak dicetak ulang pada kertas putih.
Ciri utama dari pengajian tradisional yang cuba dipertahankan dalam pesantren adalah cara pengajarannya yang ditekankan pada pemahaman literal (tekstual) atas suatu kitab kitab tertentu untuk kemudian dilanjutkan dengan pembacaan kitab lain. Cara pengajarannya pun secara umum dapat terbagi menjadi 2, pertama adalah sistem sorogan atau individual dimana seorang santri membaca sendiri kitab yang dikajinya dihadapan seorang kyai, atau sistem kedua yang disebut bandongan, yakni kyai yang membacakan kitab untuk disimak oleh santri secara berkelompok.
Pendidikan pesantren salaf tidak mengenal adanya standarisasi kelulusan berupa nilai-nilai ujian ataupun batasan waktu sebagaimana yang berlaku di sekolah umum. Santri pun memiliki kebebasan sepenuhnya untuk memilih kitab-kitab yang minat untuk dikajinya. Seorang santri yang sudah khatam dalam mengkaji satu kitab kemudian dianugerahi kebenaran (ijazah) dari sang kyai untuk mengajarkan kitab tersebut kepada orang lain yang nanti akan menjadi muridnya
Kebebasan yang dimiliki oleh santri untuk menentukan sendiri apa yang hendak dikajinya, memberikan pengaruh dalam melatih sikap untuk mandiri dan pendidikan yang ia jalani bersesuaian dengan apa yang diminatinya. Pola pendidikan tersebut sepintas lalu memang tidak selari dengan acuan-acuan yang berlaku diluar masyarakat pesantren, akan tetapi sesungguhnya hal yang demikian menghasilkan sikap yang tidak bergantung pada lembaga masyarakat manapun.
Penerapan pemahaman secara literal atas kitab-kitab yang dikajinya, secara tidak langsung mempermudah santri untuk memahami disiplin ilmu yang lain seperi nahwu, sharaf, manthiq ataupun balaghah. Dengan sistem ijazah yang diberlakukan akan menjamin materi yang diajarkan dapat dipertanggung jawabkan sebagai sesuatu yang benar-benar dapat didapatkan dari sumber-sumber terpercaya dan terus bersambung sejak daripada sang guru hingga dengan pengarang kitab tersebut (mu’allif) Hal tersebut dikenal dikalangan pesantren sebagai silsilah guru atau sanad
Disamping itu pula, pandangan hidup pesantren yang bersifat ukhrawi tentu saja dapat dijadikan alternatif sebagai pantulan kehidupan yang ideal yang didambakan oleh masyarakat dalam keadaan sekarang ini.
Terlepas dari faktor yang menjadi kelebihan sistem pengajaran di pondok pesantren, ternyata jika dikaji lebih mendalam ianya juga menyimpan beberapa faktor kelemahan seperti tidak adanya perencanaan terperinci dan rasional atas jalannnya pendidikan yang berakibat tidak adanya sistem pendidikan integral yang memiliki wawasan yang dibatasi dengan jelas.
Dengan tidak adanya sistem evaluasi baku yang diterapkan selama pembelajaran menimbulkan ketidak pastian terhadap keperluan materi-materi yang sepatutnya dikaji oleh seorang santri. Padahal, sistem evaluasi itu sangat diperlukan sebagai pijakan untuk merancang program-program pendidikan dimasa selanjutnya.
Pola pemahaman kitab yang dikaji secara literal mengakibatkan penekanan yang berlebihan terhadap pemahaman secara harfiyah dan menegasikan kemampuan untuk memahami dari sudut pandang yang lain. Dengan pola tersebut, tafsir dan teks seolah menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ditambah lagi dengan tingkat kepatuhan dan penghormatan yang sangat tinggi dari seorang santri terhadap kyai, akhirnya timbullah keyakinan bahwa apa yang diajarkan adalah kebenaran yang bersifat mutlak serta menutup dari kemungkinan terjadinya dinamisasi dalam dunia abstrak yakni dunia pemikiran. Lahirnya sikap kritis, inovatif dan kemampuan analitis juga susah untuk diharapkan dari model pendidikan seperti itu.
Dominasi pengajaran fiqh begitu menonjol dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Di lembaga pesantren, penguasaan fiqh menjadi barometer tingkat kealiman seseorang. Hal itu dapat kita pahami karena Fiqh dianggap sebagai landasan umat Islam dalam melaksanakan kehidupan keseharian samada dalam hal ubudiyah maupun interaksi sosial mu’amalah. Sisi positifnya dari fenomena itu terasa dalam pembentukan negara hukum dan masyarakat hukum akan tetapi pada sisi yang lain ia juga berpengaruh dalam menciptakan cara pandang yang normatif statis, berwatak benar-salah, ataupun hitam-putih.
D. Pergeseran Nilai-nilai di Kalangan Muslim Tradisionalis
Proses regenerasi dari generasi pendiri jam’iyah NU (KH. Hasyim Asy’ari, KH. Wahab Hasbullah dan KH. Bishri Syansuri) kepada generasi penerus setelahnya, membawa konsekuensi terjadinya “regenerasi pemikiran” dalam bentuk pergeseran pemahaman doktrin ahlussunnah wal jama’ah (aswaja) khususnya pemahaman dalam bidang fiqh yang sebelumnya menjadi identitas kelompok tradisionalis.
Tradisionalisme awalnya merupakan pertahanan diri terhadap proses kemajuan dan model modernisasi yang berlaku dan seringkali bertentangan dengan akal dan sains. Namun, untuk mencapai modernisme yang terrencana dengan menolak begitu sahaja tradisi yang sudah establish malah akan menghasilkan stagnasi total. Dengan demikian, pembangunan dan perubahan sosial tidak dapat dilakukan melalui proses diskontinuitas.
Perubahan tersebut dapat kita baca dari pergeseran pemikiran fiqh yang sebelumnya merupakan “kebenaran ortodoksi” menjadi paradigma “pemaknaan sosial”. Jika yang pertama adalah menundukkan realiti kepada kebenaran fiqh, ataupun memperlihatkan watak yang “hitam-putih”, akan tetapi pada paradigma sekarang berubah menjadi fiqh yang cuba untuk dihadirkan sebagai perangkat pemaknaan (hermeneutika) yang mempunyai relativitas sangat tinggi.
Hermeneutika bukanlah tafsir atau takwil dalam pengertian yang biasa berlaku dikalangan intelektual muslim seperti masa sebelumnya dimana pemahaman lebih terfokus pada pemahaman teks, hermeneutika berfungsi sebagai mediasi antar berbagai model pemahaman epistimologi keilmuan yang bersifat “intersubjektif” terhadap kemungkinan adanya berbagai makna dari tindakan sosial dan teks, sekaligus juga berfungsi untuk menghubungkan generasi yang hidup di era sekarang dan generasi terdahulu.
Ada lima ciri yang menonjol dalam “paradigma ber-fiqh yang baru” itu. Pertama, selalu diupayakan interpretasi ulang dalam mengkaji teks-teks fiqh untuk mencari konteksnya yang baru. Kedua,makna bermadzhab diubah yang sebelumnya secara tekstual (mazhab qauli) menjadi bermazhab secara metodologis (mazhab manhaji). Ketiga, verifikasi mendasar terhadap mana ajaran yang utama (ushul) dan mana yang cabang (furu’). Keempat, Fiqh dihadirkan sebagai etika sosial, bukan sebagai hukum positif negara, dan kelima, pengenalan metodologi pemikiran filosofis.
Ulil Abshar Abdalla menduga, bahwa “arus baru” itu secara samar telah menjalari para kyai muda diberbagai daerah yang peka terhadap perkembangan intelektual Islam avant garde, akan tetapi mereka ini tidak mau terburu-buru mengutarakan ide-ide tersebut secara terbuka karena dikhawatirkan akan bertembung dengan generasi kyai sepuh. Hal itulah yang disebut dengan pembaharuan tanpa dentuman besar, ataupun diistilahkan dengan proses silent modernism, yang sejalan dengan al-muhafadzatu ‘alal qadimi as-shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah, mempertahankan tradisi lama yang baik untuk inovasi yang lebih baik lagi.
Bersepakat dengan anggapan Ulil, Dr. Muhammad AS Hikam pun menilai, terjadi kecenderungan dikalangan kaum muda muslim sekarang, khususnya kalangan muda NU yang berkeinginan menjadikan NU sebagai gerakan Islam yang mampu menyerap enlightenment (pencerahan) walaupun prosesnya berlangsung sangat lambat, hal itu terjadi karena spektrum dalam NU yang begitu luas sehingga tak langsung nampak dipermukaan.
Permasalahan yang cuba dijawab oleh kelompok ini adalah metod apa yang sesuai digunakan untuk “mengaktualisasikan” ajaran Islam dengan modernitas, termasuk juga bagaimana cara mengkontekstualisasikan hukum Islam agar bersesuaian dengan negara yang memiliki tradisi, sejarah dan masyarakat sedemikian berbeda dengan Timur Tengah dimana Islam pertama kali diturunkan. .
Dalam rangka membongkar kemapanan tradisi yang hampir menjadi ortodoksi itu, Muhammad Abed al-Jabiri memberikan tiga metod alternatif yang sepatutnya dicuba, yakni pertama melakukan metod strukturalis, ertinya dalam mengkaji sebuah tradisi kita berangkat dari teks-teks sebagaimana adanya, selanjutnya melakukan analisis sejarah, ini berkaitan dengan upaya untuk mencari kebenaran hakiki maksud dari sebuah teks setelah kita melalui proses yang pertama tadi. Dengan menganalisa sejarah berarti kita mempertimbangkan ruang lingkup budaya, politik dan sosial pada saat teks diturunkan, dan ketiga adalah kritik ideologi, maksudnya mengungkap fungsi ideologis termasuk fungsi sosial-politik yang dikandung sebuah teks atau pemikiran tertentu.
Kelompok yang muncul terakhir ini banyak memperoleh sebutan seperti misalnya neo-modernis, Islam aktual, Islam Substantif, Islam Peradaban dan (dalam hal ini penulis lebih suka menggunakan istilah) Kelompok Post-Tradisionalis (postra). Mereka semua mendasarkan perhatiannya kepada membangun visi Islam dimasa moden dengan sama sekali tidak meninggalkan tradisi (warisan) intelektual Islam. Bahkan jika mungkin mencari akar-akar Islam untuk mendapatkan kemodenan Islam itu sendiri. Hal itu berbeda dengan kaum “modernis lama” yang lebih bersifat apologetik terhadap gagasan modernitas dengan menegasikan langsung adanya tradisi yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat.
Menurut Rumadi dalam bukunya, Post Tradisionalisme Islam: Wacana Intelektualisme dalam Komunitas NU, spirit dari gerakan postra adalah membangkitkan kembali tradisi untuk tidak bersikap pada tradisionalisme yang jumud, tetapi juga tidak menafikan tradisi untuk membangun pemikiran modernis yang kaku. Postra, di dalam dirinya, mengandung pengertian kontinuitas dan perubahan. Kontinuitas dalam arti menggunakan tradisi sebagai basis untuk melakukan transformasi. Dalam kontinuitas itu, dimungkinkan adanya kritik tradisi baik yang berasal dari dalam Islam dan NU sendiri maupun dari khazanah tradisi lain (Arab dan Barat). Tradisi dibongkar bukan untuk dibenci, melainkan diwujudkan kembali dalam rangka diperkaya untuk perubahan.
Wallahua’lam.
Daftar Pustaka:
Abdurrahman Wahid Menggerakkan Tradisi: Esai-esai Pesantren, Jogjakarta: LKiS (2001)
Ahmad Suaedy, Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi, Jogjakarta: LKiS, (2000)
Ali Maschan Moesa Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama, Jogjakarta: LKiS, (2007)
Ali Yafie, KH. Prof., Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan, Jogjakarta, LKPSM (1997)
Alwi Shihab, Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia, Bandung: Mizan (1998)
Amien Rais, Dr. Refleksi Amien Rais Dari Persoalan Semut Sampai Gajah, Jakarta: Gema Insani Press, cet: 2 (1997)
Amin Idris KH. Noer Muhammad Iskandar, SQ: Pergulatan Membangun Pondok Pesantren, Jakarta: Asshidiqiyah Press, (2003)
-----------------, Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta, Bandung: Mizan (1987)
Anang Haris Himawan S.Ag. (ed): Epistimologi Syara’ Mencari Format Baru Fiqh Indonesia, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, (2000)
Andree Feillard, NU vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna, Jogjakarta: LKiS, (1999)
Badrun Alaena, NU: Kritisisme dan Pergeseran Makna Aswaja, Jogjakarta: PT. Tiara Wacana, (2000)
Budhy Munawar Rachman, Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman, Jakarta: Paramadina, (2001)
Choirul Anam Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama, Solo: Jatayu Sala (1985)
Fadhullah Jamil, Prof.Madya Islam Zaman Moden: Cabaran dan Konflik, Selangor: Thinker’s Library Sdn Bhd. (1997)
Faisal Ismail, H. Prof. Dr. MA, , Ketegangan Kreatif Peradaban Islam Idealisme Versus Realisme, Jakarta: PT. Bakti Aksara Persada (2003)
Greg Barton dan Greg Fealy (ed): Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama – Negara, Jogjakarta: LKiS (1996)
Hamdan Farchan & Syaifuddin, Titik Tengkar Pesantren: Resolusi Konflik Masyarakat Pesantren, Yogyakarta: Pilar Media, (2005)
Hassan Hanafi Cakrawala Baru Peradaban Global: Revolusi Islam Untuk Globalisasi, Pluralisme dan Egalitarianisme Antar Peradaban, Jogjakarta: IRCiSoD (2003)
http://64.203.71.11/kompas-cetak/0311/17/swara/689879.htm
Lathiful Khuluq, MA, , Fajar Kebangunan Ulama: Biografi KH. HAsyim Asy’ari, Jogjakarta: LKiS, (2000)
M.T. Arifin, Gagasan Pembaharuan Muhammadiyah, Jakarta: Pustaka Jaya (1987)
MA. Sahal Mahfudh Nuansa Fiqh Sosial, Jogjakarta: LKiS (1994)
Marzuki Wahid, et.al: Geger di “Republik” NU Perebutan Wacana, Tafsir Sejarah, Tafsiran Makna, Jakarta: Lakpesdam NU (1999)
Mohammad Damami, , Akar Gerakan Muhammadiyah, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru (2000)
Mu’arif, Meruwat Muhammadiyah; Kritik Seabad Pembaruan Islam di Indonesia, Yogyakarta: Pilar Media (2005)
Muhammad Abed al-Jabiri, Post-Tradisionalisme Islam, Jogjakarta: LKiS, hlmn.19-21 (2000)
Nur Achmad dan Pramono U. Tanthowi (ed.), Muhammadiyah “Digugat” Reposisi Di Tengah Indonesia Yang Berubah, Jakarta: PT. Gramedia (2000)
Nur Kholik Ridwan, Agama Borjuis, Kritik Atas Islam Murni, Jogjakarta: AR-Ruzz Media,(2004)
Nurcholis Madjid, Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan, Bandung: Mizan, (1987)
Pradjarta Dirdjosanjoto, Memelihara Umat: Kiai Pesantren - Kiai Langgar di Jawa, Jogjakarta: LKiS (1999)
Prof. Azyumardi Azra, M.A. Renaisans Islam Asia Tenggara, Sejarah Wacana dan Kekuasaan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, (1999)
Said Aqiel Siradj et.al, Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren, Bandung: Pustaka Hidayah, (1999)
Sukamto, Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren, Jakarta: Pustaka LP3ES, (1999)
Syaifullah, , Gerak Politik Muhammadiyah Dalam Masyumi, Jakarta: Pustaka Utama Grafitti (1997)
Thalhas, TH, Dr., Alam Pikiran KH. Ahmad Dahlan & KH. M. Hasyim Asy’ari, Jakarta: Galura Pase (2002)
Ulil Abshar Abdalla, Membakar Rumah Tuhan Pergulatan Agama Privat dan Publik, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya (1999)
Umaruddin Masdar, Gus Dur: Pecinta Ulama Sepanjang Zaman, Pembela Minoritas Etnis-Keagamaan, Jogjakarta: Klik.R, (2005)
Zainal Abdidin Bagir et.al (ed): Integrasi Ilmu dan Agama, Bandung:Mizan (2005)
Zamakhsyarie Dhofier Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, Jakarta: LP3ES (1982)
Zulkifli, Kontinuitas Islam Tradisional di Bangka, Bangka Belitung: Shiddid Press, (2007)
skip to main |
skip to sidebar
Silahkan Kirim Artikel Anda Kpd Kami bisa melalui Email darussholah@gmail.com
WebLink
Label
- Kata Mutiara (6)
- Keagamaan (52)
- Khutbah Jum'at (15)
- Pendiri Darus Sholah (8)
- Terjemahan Kitab Aswaja (1)
- Tokoh (14)
- Wawasan (3)
Artikel Populer
- KHUTBAH JUM’AT BULAN SYAWAL
- KHUTBAH JUM’AT BULAN SHAFAR
- KHUTBAH JUM’AT BULAN MUHARRAM
- KHUTBAH JUM’AT BULAN DZULQO’DAH
- APLIKASI METODE DISCOVERY LEARNING DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMECAHKAN MASALAH, MOTIVASI BELAJAR DAN DAYA INGAT SISWA
- KHUTBAH JUM’AT BULAN RAJAB
- KEMU'JIZATAN AL-QUR'AN DARI SEGI BAHASA & ISYARAT ILMIYAH
Buku Tamu
Copyright © 2011 Darus Sholah Jember | Powered by Blogger


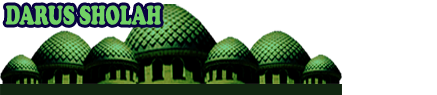
 19.43
19.43
 darussholah
darussholah

 Posted in:
Posted in:
0 komentar:
Posting Komentar