Penulis : Abdul Qodir
Adalah Pancasila yang tiap butirnya mampu menyatukan aspek pluralitas bangsa menjadi satu kesatuan visi bernegara. Sebagai bangsa yang sadar akan hak-hak tiap warganya yang tidak hanya terdiri dari satu warna, Indonesia mampu mengemas berbagai macam ketidak-samaan menjadi suatu nilai positif dengan mengunggulkan kekayaan berbagai macam budaya yang lahir di dalamnya. Selama lebih dari enam dekade terakhir ini Pancasila secara struktural mampu mempertahankan eksistensinya sebagai ideologi dasar Republik Indonesia. Namun ironisnya, pemahaman serta peran Pancasila dalam kehidupan masyarakat agaknya mulai kentara kerapuhannya. Hal ini tidaklah dikarenakan Pancasila tidak lagi sesuai jika diterapkan dalam konteks kekinian, melainkan ketidak sempurnaan pembacaan serta pemahaman terhadap ideologi bangsa tersebut.
Betapa tidak, sebuah Negara yang dibangun di atas ragamnya perbedaan, kini ingin dijadikan satu pandangan yang tidak jelas kemana arahnya. Keprihatinan ini bermula ketika Agama dibenturkan dengan Negara (permasalahan ketidak-harmonisan antara agama dan Negara bukanlah satu-satunya permasalahan bangsa, namun merupakan satu diantara sekian banyaknya problematika yang ada). Sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”, bukanlah milik satu agama saja, melainkan milik semua agama yang berkembang di Indonesia. Jika sedikit menoleh ke belakang mengenai sejarah terbentuknya ideologi dasar negara Indonesia, mulanya sila pertama itu berbunyi—sebagaimana yang tertuang dalam piagam Jakarta— “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Beberapa kalangan keberatan dan mengganti tujuh kata yang menjadi kontroversi dengan kata-kata “yang Maha Esa”. Bila perdebatan yang berlangsung selama proses perumusan tersebut dicermati lebih dalam lagi, pesan yang ingin disampaikan ialah adanya upaya untuk menghindari terbentuknya negara sekuler, negara yang terpisah dengan urusan agama. Sebaliknya, dengan perumusan semacam itu juga bukan berarti ingin mewujudkan negara agama. Jalan tengah yang dipilih adalah sebuah negara yang tidak sekuler sekaligus tidak mendasarkan pada agama tertentu. Hal ini merupakan solusi tepat, mengingat masyarakat Indonesia ialah masyarakat berbudaya, beragama dan bermoral—yang tidak kalah santunnya dengan Negara Arab saudi—sehingga apabila dibawa ke arah sekuler maka akan menghilangkan nilai-nilai budaya luhur yang sudah tertanam kuat dalam praktek beragama para penduduknya. Dan juga membaca ragamnya agama yang dianut, sehingga pilihan menjadikan Pancasila sebuah ideologi negara merupakan keputusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Kenyataan pahit bagi ibu pertiwi jika di tengah harmonisnya hubungan antara agama dan negara kemudian muncul sebagian anak bangsa yang meneriakkan “Tegakkan Syari’ah di Indonesia” dan dengan semaunya sendiri ingin mengubah Pancasila dengan syari’at Islam dalam perspektif mereka. Bendera merah putih yang dijahit oleh tangan lembut Ibu Fatmawati seakan terkoyak dan terinjak lusuh di tengah tanah perjuangan. Ketidak sadaran akan nilai-nilai luhur pancasila sebagai tuntunan filosofis negara menjadikannya seperti bersebrangan dengan Agama Islam yang mereka pahami. Tidak hanya itu, perbedaan sudut pandang dalam menilai Agama juga ikut andil dalam mewujudkan keinginan terbentuknya Negara Islam. Potret Islam santun yang digambarkan oleh penyebar Islam pertama di Nusantara tak lagi terlihat, Islam yang tidak menghancur-leburkan tradisi lokal kini mulai terkikis dengan Islam impor yang mengagungkan budaya Luar (Arab).
Sebuah tanda tanya besar memang, apakah kita ber-Islam harus mengganti Pancasila dengan Syari’at Islam (dengan ditegakkannya Khilafah ataupun Daulah)? Padahal tiap negara pastilah berbeda kebijakan yang dihasilkan dari interaksi masyarakat dengan produk budaya yang ada. Nilai-nilai kesantunan pun tentunya tidak sama antara negara satu dengan negara lain. Sehingga syari’at Islam yang dijadikan sebagai UUD Madinah pada saat Rasulullah memimpin negara bukanlah jawaban tepat atas segala problem ke-Indonesia-an. Pembacaan semacam ini terkadang tertolak keras dengan ayat yang menurut mereka melegitimasi pendapat tegaknya syari’ah, “Wa man lam yahkum bima anzala Allah Faulaika hum al-dhalimun” (al-Maidah [5]: 45). Klaim Kafir pun tidak segan-segan disematkan kepada orang yang tidak mendukung tegaknya syari’ah dalam sebuah negara.
Pertanyaan lain muncul yang erat kaitannya dengan perbedaan budaya. Haruskah kita suka korma?? Padahal lidah kita lebih terbiasa dengan ketela. Haruskah kita mengganti batik dengan jubah?? Sedangkan batik merupakan karya agung nenek moyang kita yang harus kita lestarikan warisannya. Haruskah kita berjenggot dengan membeli obat penumbuh jenggot ketika kita secara genetik tidak berjenggot?? Apakah seperti itu yang diinginkan Islam??
Sebagai anak bangsa yang rindu akan semangat nasionalisme, tidak tahu apa lagi yang harus diperbuat. Hanya bisa tertulis sebuah harapan besar semoga Indonesia akan tetap menjadi Indonesia. Semuslim apapun kita, haruslah kita ingat, bahwa udara yang kita hirup ialah udara Indonesia. Tanah yang kita jadikan pijakan ialah tanah air Indonesia. Kita masih tetap anak ibu pertiwi yang harus mempertahankan nilai luhur kebudayaan yang ada di dalamnya.
skip to main |
skip to sidebar
Silahkan Kirim Artikel Anda Kpd Kami bisa melalui Email darussholah@gmail.com
WebLink
Label
- Kata Mutiara (6)
- Keagamaan (52)
- Khutbah Jum'at (15)
- Pendiri Darus Sholah (8)
- Terjemahan Kitab Aswaja (1)
- Tokoh (14)
- Wawasan (3)
Artikel Populer
- KHUTBAH JUM’AT BULAN SYAWAL
- KHUTBAH JUM’AT BULAN SHAFAR
- KHUTBAH JUM’AT BULAN MUHARRAM
- KHUTBAH JUM’AT BULAN DZULQO’DAH
- APLIKASI METODE DISCOVERY LEARNING DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMECAHKAN MASALAH, MOTIVASI BELAJAR DAN DAYA INGAT SISWA
- KHUTBAH JUM’AT BULAN RAJAB
- KEMU'JIZATAN AL-QUR'AN DARI SEGI BAHASA & ISYARAT ILMIYAH
Buku Tamu
Copyright © 2011 Darus Sholah Jember | Powered by Blogger


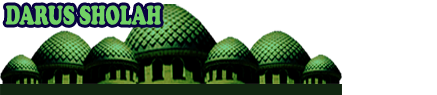
 09.18
09.18
 darussholah
darussholah

 Posted in:
Posted in:
0 komentar:
Posting Komentar