Penulis : Rizki Amalia
Dalam Islam tidak bisa dipungkiri bahwa seseorang akan selalu membenarkan terhadap mazdhab tertentu tanpa harus menyampingkan mazdhab lain, selama apa yang diyakini itu tidak mengucilkan terhadap Islam, tidak mengurangi esensi agama, tidak menghilangkan syari’at Allah, tidak membatasi ketentuan-ketentuan Allah, tidak menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan tidak mengharamkan apa yang di halalkan-Nya. meskipun itu hanya dalam sektor kecil dari beberapa sektor yang ada.
Begitulah agama Islam, agama yang tidak pernah memaksakan kehendak, pemikiran siapapun baik pada zaman Rasulullah, ulama salaf (terdahulu), ulama khalaf (modern), pada masa sekarang sekalipun. Baginda Rasulullah Saw. adalah teladan dalam hal ini, beliau tidak pernah memaksakan pemikiran, tidak pernah menyeru pemikiran yang keluar dari Al-Qur’an, tidak mengharuskan seseorang dengan satu pendapat saja, beliau senantiasa membuka peluang untuk selalu ber-ijtihad apa yang tidak ada dalam syariat, selalu melapangkan dan memberi kesempatan kepada para sahabatnya untuk mengeluarkan pendapat.
Seperti apa yang terjadi dalam perang Badar Kubro, Rosulullah meminta sahabat Muhajirin untuk berpendapat lebih dulu mengenai setrategi perang, kemudian beliau juga meminta pendapat kepada sahabat Ansor. Namun ketika terjun dalam medan perang ternyata setrategi tersebut tidak bisa dijalankan kerena jumlah pasukan kaum muslimin tidak sebanding dengan pasukan kaum musyrikin. Rosulullah menerapkan strategi yang dikemukakan oleh Al-Habbab bin Al-Mudadzir ra. Karena strategi itu dinilai lebih sesuai dengan kondisi pada waktu itu. Ini adalah merupakan cara dasar dalam pengaturan strategi sosok panglima perang. Dengan memberi kesempatan kepada semua prajurit yang punya pendapat dalam mengalahkan pasukan musuhnya.
Hal yang sama juga bisa dilihat ketika Rosulullah meminta pendapat kepada sahabatnya dalam memperlakukan tawanan perang Badar. Saidina Abu Bakar berpendapat dengan mengambil fidyah (pajak) dari mereka, fungsinya untuk membangun kekuatan pasukan muslim dari serangan musuh. Sedangkan Saidina Umar berpendapat para tawanan itu lebih baik dibunuh, karena mereka adalah para pembesar kaum kafir, pendapat saidina Umar lebih sesuai dengan Al-Quran tapi Rosulullah lebih condong kepada pendapat Saidina Abu Bakar. Walaupun Rosulullah kurang sependapat dengan saidina Umar, tidak lantas beliau mencela pendapatnya.
Contoh lagi tatkala Rosulullah menerima pendapat saidina Salman Al-Farisi dalam perang Khondaq, Al-Farisi mengusulkan untuk membuat parit yang dapat menghalau gabungan pasukan kafir untuk memasuki atau memporak porandakan kota Madinah. Ketika Rosulullah selesai menghadapi perang Khodaq atau bisa disebut perang Ahzab. Allah telah membantu orang-orang muslim dengan pasukan-Nya. Begitu Rosulullah selesai mengkalkulasi kurban perang, tiba-tiba beliau didatangi saidina Jibril seraya berkata: “kamu telah meletakkan senjatamu tapi para malaikat belum mau meletakkan senjatanya, sesungguhnya Allah mengutusmu untuk melakukan perjalanan menuju Bani Quroidzhoh, aku juga menuju kesana untuk memerangi mereka, karena Bani Quraidzhoh memiliki peranan besar dalam ikut menyerang kaum muslimin, bahkan mereka termasuk golongan yang sangat memusuhi kaum muslim”. Kemudian Rosulullah memerintahkan pasukanya sembari berkata: “barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, jangan melakukan sholat ashar kecuali sesampai di Bani Quraidzhoh”. Berangkatlah kaum muslimin menuju Bani Quraidhoh dengan mengumumkan pesan Rosulullah tersebut. Ditengah perjalanan tibalah waktu sholat ashar, sebagian dari kaum muslimin melakukan sholat ashar sebelum sesampainya di Bani Quraidzoh, karena mereka memahami maksud dari ucapan Rosulullah agar sesegera mungkin menuju peperangan tanpa ada keterlambatan. Sebagian yang lain menangkap ucapan Rosulullah tersebut secara tekstual dan tidak melaksanakan sholat setelah sesampainya di bani Quraidzhoh.
Kejadian yang berlawanan ini tidak semerta-merta membuat perpecahan dikalangan kaum muslimin. Mereka tidak saling mencela meskipun memiliki pemahaman berbeda, mereka dapat saling menghormati antara satu dengan yang lain. Gambaran ijtihad yang jelas ini memang diajarkan dan direstui oleh baginda Rosulullah Saw. Rosulullah tidak menyalahkan atau mencela salah satu dari mereka.
Ajaran Rosulullah mengenai cara berijtihad masih banyak terdapat dalam kejadian-kejadian lain, yang memberi isyarat kepada kita akan luasnya sektor kehidupan yang diperlukan untuk berijtihad pada masa kenabian. Yaitu untuk mengeluarkan pendapat tanpa mencela atau merendahkan dan menghina pendapat lain.
Sifat keterbukaan itu digambarkan juga oleh para generasi setelah beliau. Saidina Umar berpendapat akan pentingnya pengumpulan Al-Qur’an (kodifikasi) ketika beliau melihat terbunuhnya para penghafal Al-Qur’an yang mana hal ini akan menyebabkan hilangnya Al-Qur’an setelah sepeninggal mereka.
Ini bisa dilihat dalam hadist yang diriwayatkan oleh saidina Zaid bin Tsabit ra. Beliau berkata telah sampai informasi kepada saidina Abu Bakar, tentang beberapa khuffad (para penghafal Al-Qur’an) yang terbunuh pada peperangan Yamamah. Dan pada waktu itu saidina Umar bin Khotob sedang bersama saidina Abu Bakar, kemudian saidina Umar berkata: “Pembunuhan telah menimpa beberapa Quro’ul Qur’an pada perang Yamamah dan sungguh aku takut pembunuhan para qura’ juga terjadi di berbagai tempat, maka akan semakin banyak hilangnya para penghafal Al-Qur’an, menurutku hendaknya engkau memerintahkan pengumpulan (Kodifikasi) Al-Qur’an”. Lalu aku berkata kepada saidina Umar: bagaimana kamu melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rosulullah. Saidina Umar menjawab: Demi Allah, menurutku ini adalah jalan yang terbaik. Tetapi saidina Umar tidak pernah meminta pendapat kepadaku, (Zaid bin Tsabit) sampai akhirnya Allah membuka hatiku dan hati saidina Abu Bakar, akhirnya aku sependapat dengan ide beliau. Lalu saidina Abu Bakar berkata kepadaku: “Kamu adalah pemuda yang pandai, bagaimana jika kamu yang menulis, dan mengumpulkan wahyu yang telah disampaikan kepada Baginda Rosulullah”. Demi Allah seandainya mereka menyuruhku untuk memindahkan sebuah gunung maka mengumpulkan Al-Qur’an itu adalah pekerjaan yang lebih berat.
Kemudian mulailah pengumpulan Al-Qur’an yang tercecer ditulis di dedaunan, tulang, dari di benak para penghafal Al-Qur’an. Pengumpulan Al-Qur’an mula-mula menurut saidina Abu Bakar dan saidina Zaid bin Tsabit adalah bid’ah. Akan tetapi keduanya tidak seraya mencela saidina Umar, dan tidak seorangpun dari mereka menuduh saidina Umar melakukan bid’ah.
Fenomena serupa juga terjadi pada masa pemerintahan saidina Umar tatkala saidina Kholid bin Walid mengutus seseorang untuk menanyakan tentang hukuman peminum khomer.
Hadist ini Diriwayatkan dari saidina Hamid bin Abdurahman dari ayahnya, berkata: aku diutus sadina Kholid bin Walid untuk datang ke saidina Umar ra. Kemudian aku mendatanginya pada sa’at saidina Umar berada di masjid bersama saidina Utsman ra, saidina Ali ra, saidina Abdurrahman bin Auf ra, saidina Tolhah ra, dan saidina Zubair ra. Mereka sedang duduk bersandar di depan masjid kemudian aku menghadap seraya berkata: sadina Kholid bin Walid mengutusku untuk datang kepadamu, beliau menyampaikan salam kepadamu bahwa masyarakat banyak yang meminum khomer. Kemudian saidina Umar berkata, “Kamu berhak untuk memisahkan mereka dari khomer”, saidina Ali juga berkata: “Tatkala seseorang meminum khomer dia akan mengigau, ketika mengigau dia akan mengatakan hal-hal yang tidak benar, dan orang seperti ini layak dicambuk delapan puluh kali”. Lalu saidina Umar kembali berkata “sampaikan apa yang dikatakan saidina Ali kepada Kholid bid Walid”.
Saidina Kholid bin Walid-pun mencambuk setiap orang yang meminum khomer sebanyak delapan puluh kali, begitu juga yang dilakukan saidina Umar. Akan tetapi saidina Umar membedakan jumlah cambukan antara orang yang memiliki tubuh kuat dengan yang memiliki tubuh lemah. Apabila si peminum memiliki tubuh kuat dan dia benar-benar sudah terjerumus, beliau mencambuknya sebanyak delapan puluh kali, manakala si-peminum bertubuh lemah dan minum karena khilaf saidina Umar mencambuknya sebanyak empat puluh kali. Lain lagi dengan saidina Utsman, beliau mencambuk sebanyak delapan puluh empat kali.
Dalam hal perbedaan jumlah cambukan ini tidak seorangpun dari sahabat yang menuduh mereka yang berbuat bid’ah padahal semasa baginda Rosulullah masih hidup, jumlah cambukan hanya berjumlah empat puluh kali.
Inilah etika (yang patut diteladani) dalam menyikapi perbedaan yang muncul di masa para sahabat Rosulullah, di masa itu seringkali terjadi perbedaan pendapat yang krusial, baik aqidah ataupun syari’ah. Akan tetapi para sejarawan tidak pernah menuliskan bahwa salah seorang dari mereka pernah menyematkan tuduhan kafir, zindiq, atau fasiq. Padahal sebagian mereka ada yang tidak memakai hadist Rosulullah yang notabene sohih. Jika kita mau membuka kembali buku-buku fiqih atau aqidah, kita tidak menemukan seorang ulama’ pun yang menyematkan tuduhan negatif, bahkan mereka berusaha introspeksi diri, barangkali dalam pemahaman nash atau penggunaan dalil terdapat kekurangan ataupun kesalahan.
Salah satu sosok yang memiliki jiwa besar seperti itu adalah Imam Abu Hanifah. Sebagaimana apa yang diucapkan oleh Imam Syafi’i. banyak ulama’ yang kagum terhadap cara berfikirnya Imam Abu Hanifah. Beliau berusaha menghilangkan fanatisme terhadap sebuah pendapat, beliau selalu membuka ruang dan kesempatan bagi orang lain untuk mengeluarkan pendapatnya. Imam Abu Hanifah pernah berkata: “ucapan kami ini adalah pendapat kami, menurut kami ini benar, bila ada seseorang memiliki pendapat yang lebih baik dan lebih benar, maka pendapat itulah yang berhak diambil”.
Pada suatu ketika ada salah seorang yang tidak setuju dan mengatakan kepada Imam Abu Hanifah: “Wahai Imam.. apakah fatwa yang engkau keluarkan ini adalah benar, tidak ada keraguan lagi?”. Kemudian Imam Abu Hanifah menjawab: “Demi Allah aku tidak tahu, bisa jadi fatwaku itu salah, tidak ada keraguan lagi. Begitulah cara Imam Abu Hanifah memberi peluang yang lain untuk berpendapat.
Begitu pula dengan Imam Syafi’i beliau adalah sosok yang meletakkan konsep penting dalam tata cara berdialog, menghindari fanatisme dan tidak mudah mencela pendapat orang lain. Imam Syafi’i pernah mengutarakan: “Pendapat kami benar adanya, tapi memungkinkan adanya kesalahan, pendapat dari orang selain kami salah adanya tapi memungkinkan adanya kebenaran”. Konsep inilah yang ditempuh dan diletakan oleh para ulama salaf, hendaklah menjadi teladan bagi kita dalam menyikapi perbedaan yang berkembang di segala aspek kehidupan, dengan bersifat dialogis, tidak mencela pemikiran lain, serta tidak memaksa seseorang untuk mengikuti pendapat kita, agar roda kehidupan senantiasa berjalan di atas jalur yang benar, toleran, mengakui perbedaan pendapat dan menghargai sesama. [ř]
[Disarikan dari artikel DR. Abdul Fatah Mahmud Idris dalam Majalah Al-Mujahid, edisi 334 - maret 2008 oleh Rizki Amalia, Aktifis Forsida dan Alumni PP.DS]
skip to main |
skip to sidebar
Silahkan Kirim Artikel Anda Kpd Kami bisa melalui Email darussholah@gmail.com
WebLink
Label
- Kata Mutiara (6)
- Keagamaan (52)
- Khutbah Jum'at (15)
- Pendiri Darus Sholah (8)
- Terjemahan Kitab Aswaja (1)
- Tokoh (14)
- Wawasan (3)
Artikel Populer
- KHUTBAH JUM’AT BULAN SYAWAL
- KHUTBAH JUM’AT BULAN SHAFAR
- KHUTBAH JUM’AT BULAN MUHARRAM
- KHUTBAH JUM’AT BULAN DZULQO’DAH
- APLIKASI METODE DISCOVERY LEARNING DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMECAHKAN MASALAH, MOTIVASI BELAJAR DAN DAYA INGAT SISWA
- KHUTBAH JUM’AT BULAN RAJAB
- KEMU'JIZATAN AL-QUR'AN DARI SEGI BAHASA & ISYARAT ILMIYAH
Buku Tamu
Copyright © 2011 Darus Sholah Jember | Powered by Blogger


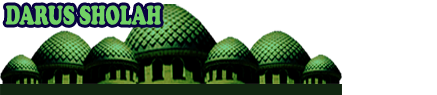
 08.06
08.06
 darussholah
darussholah

 Posted in:
Posted in:
0 komentar:
Posting Komentar