WACANA NEO-SUFISME DALAM ISLAM
(Pendekatan ke Arah Dekonstruksi Tasawuf)
Oleh : M.Syamsudini , M.Ag.
PROLOG
Berangkat dari asumsi bahwa masyarakat moderen sering digolongkan sebagai the post industrial society, suatu masyarakat yang telah mencapai tingkat kemakmuran hidup material yang sedemikian rupa dengan perangkat teknologi yang serba mekanik dan otomat, bukannya semakin mendekati kebahagiaan hidup, melainkan sebaliknya kian dihinggapi rasa cemas dan krisis moral akibat kemewahan hidup yang diraih-nya. Mereka telah menjadi pemuja ilmu dan teknologi, sehingga tanpa disadari integritas kemanusiaannya tereduksi, bahkan lalu terperangkap pada jaringan sistem rasionalitas teknologi yang sangat tidak manusiawi.
Persoalan serius yang muncul di tengah-tengah umat manusia sekarang ini adalah krisis spiritualitas. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dominasi rasionalisme, empirisme dan positivisme ternyata membawa manusia kepada kehidupan moderen, di mana sekularisme menjadi mentalitas zaman, dan karena itu spiritualisme tereduksi dari dalam kehidupan moderen umat manusia. Seyyed Hosein Nasr menyayangkan lahirnya keadaan ini sebagai the plight of modern men, nestapa orang-orang moderen (Nasr, 1987). Kondisi inilah yang tampaknya membuat masyarakat Barat pada umumnya mengalami apa yang disebut dengan krisis epistimologis, yakni masyarakat Barat tidak lagi mengetahui tentang makna dan tujuan hidupnya (meaning and purpose of life) (Madjid, 1992,580-581) dan (Madjid, 1984, 71). Hal ini bisa jadi karena terbatasnya bahasa ilmiah untuk mengungkapkan kompleksitas dunia manusia atau dengan kata lain boleh jadi karena kesenjangan antara scientific language dengan religious language.
Namun di era globalisasi ini, saat fajar menjelang tahun 2000, tidak dapat diragukan lagi tampak tanda-tanda kebangkitan kembali agama (religious revivalism). Masalah-masalah spiritualitas mulai terlihat kembali dibicarakan banyak orang, karena memiliki kesempatan yang jauh lebih besar untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Fenomena ini sekaligus sebagai pertanda bahwa umat manusia mulai lagi membicarakan dan mencari tentang makna dan tujuan hidup. Harun Nasution mengungkap hal ini lebih jauh sebagai berikut :
Pada akhir-akhir ini, banyak pula orang yang mencari keruhanian kembali. Ada yang pergi ke agama semula sungguhpun tidak dengan keyakinan penuh. Terdengar ungkapan seperti ini: Saya sebenarnya kurang percaya kepada agama saya, tetapi dalam kekacauan nilai yang di bawa kemajuan iptek moderen sekarang, saya harus mempunyai pegangan. Kalau tidak, kehidupan saya akan mengalami kekacauan. Ada pula yang pergi ke agama lain, terutama yang ada di Timur, karena agama yang berkembang di Barat, sudah banyak pula dipengaruhi kematerian yang melanda masyarakat itu. Ada pula yang pergi ke gerakan keruhanian di luar agama. Ada pula yang mencari keruhanian pada para psikologi, bahkan menurut informasi terakhir ada yang pergi ke sihir. Hidup kematerian ternyata tidak memuaskan. Di samping hidup kematerian diperlukan hidup keruhanian. Literatur keagamaan dan keruhanian mulai dicari kembali. (Nasution, 1995,114).
Berhubungan dengan masalah ini, William McInner juga menyatakan bahwa perkembangan baru dalam agama pada abad ke-21 mendatang antara lain ditandai oleh perkembangan spiritual yang lebih mendalam (McInner, 1990,85). Apa yang dikemukakan McInner ini bukanlah sesuatu yang berlebihan, sebab manusia kontemporer menghadapi penyakit teralieniasi (alienation men) dan terjadi split personality. Fakta ini menunjukkan bahwa di kalangan Barat sendiri mulai ada kekuatan yang lebih komprehensip dan integral. Makin banyak orang menanyakan kebenaran dari dominasi rasio dan lebih menginginkan kehidupan yang utuh. Perhatian terhadap kehidupan religious makin bertambah dan materialisme makin didesak oleh nilai-nilai yang transendental.
Masalahnya sekarang adalah agama dan spiritualitas yang bagaimana yang kondusif untuk dunia moderen. Jangan-jangan spiritualisme bebas seperti yang diramalkan oleh John Naisbitt dan Patricia Aburdene dengan jargonnya Spiritualitas Yes, Organized Religion No. (Naisbitt, 1991, 295). Hal yang menarik menurut pandangan Arnold (Hidayat,dan Nafis, 1995, 116-117) adalah ia mengatakan bahwa agama yang cocok untuk dunia moderen adalah keberagamaan kaum sufi.
Sekalipun krisis spiritualitas menjadi ciri peradaban moderen, dan modernitas itu telah memasuki dan menjamah dunia Islam, masyarakat Islam tetap menyimpan potensi untuk menghindari krisis itu. Sebab sebagian besar dunia Islam belum berada pada tahap perkembangan kemajuan negara-negara Barat. Keadaan ini sangat menguntungkan dunia Islam, karena memiliki kesempatan untuk belajar dari pengalaman mereka dan membangun strategi management of ideas, yang mampu mengambil aspek-aspek positif dari peradaban Barat dan sekaligus menghilangkan aspek-aspek negatifnya. Hal ini bisa dilakukan dengan mempertahankan dasar-dasar spiritualisme Islam agar tetap terjaga kehidupan yang seimbang/ummatan wasathon (QS.Ali Imran/3:143).
Dalam sejarah Islam, sufisme adalah khazanah spiritualisme Islam yang sangat berharga. Ia berkembang mengikuti dialektika zaman sejak Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, baik dalam bentuknya yang sederhana dan ortodoks, maupun yang elaborate dan heterodoks. Perkembangan sufisme ini boleh jadi mencerminkan ragamnya pemahaman yang lebih sempurna terhadap konsep akhlak dalam kehidupan sosial dan konsep ihsan dalam kehidupan spiritual, atau boleh jadi hanya sebagai eskapisme (pelarian) dalam dunia moderen karena ketidak berdayaan menghadapi pergulatan hidup. Terlepas dari trend mana yang benar dari dua sudut pandang di atas, tulisan ini akan berupaya mencari dan mereformulasikan atau merekonstruksi konsep-konsep spiritualisme Islam atau sufi yang berkembang selama ini. Atau berupaya menemukan bagaimanakah konsep spiritualisme Islam atau tasawuf yang kontekstual dan kondusif untuk kehidupan moderen atau post-moderen ini?
POTRET SUFI ; Sekilas Pendekatan Historis
Dikalangan ahli tasawuf terjadi perbedaan pendapat tentang asal-usul ajaran tasawuf. Ada yang mengatakan bahwa tasawuf Islam itu bersumber dari ajaran di luar Islam. Dan ada pula yang berpendapat bahwa tasawuf Islam murni berasal dari ajaran Islam.
R.A. Nicholson, sejarahwan dan ahli mistisisme dalam Islam, misalnya, cenderung mengatakan bahwa tasawuf Islam tidaklah murni berasal dari ajaran Islam, tetapi banyak mengambil dari para sufi agama lain. Selanjutnya ia memandang bahwa tasawuf Islam dipengaruhi oleh agama Nasrani. Ia menunjuk pada perjalan kehidupan sufi yang zuhud, senang pada kesunyian, suka memakai pakaian dari bulu domba, atau banyak berdzikir dan lain-lain. Hal ini mempunyai kesamaan dengan ajaran agama Nasrani. Di sisi lain ia melihat pula adanya pengaruh Neo Platonisme dan pengaruh Budha dalam ajaran tasawuf Islam (Nicholson, 1947,28 dan Nicholson,1975,10-13).
Dalam hal ini, menurut Harun Nasution, benar tidaknya teori yang mengatakan bahwa tasawuf merupakan ajaran yang tidak murni dari sumber ajaran Islam sulit dibuktikan. Yang jelas menurutnya, baik ada pengaruh dari ajaran agama-agama tersebut maupun tidak, sufisme dapat saja tumbuh dalam Islam. (Nasution, 1992, 59). Hal ini mengingat di dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang tampaknya sesuai atau sejalan dengan ajaran tasawuf, misalnya bahwa manusia itu dekat sekali dengan Tuhan (QS. al-Baqarah/2:186, Qaf/50/16), tentang mujahadah al-nafs (QS.al-Ankabut/29:69, al-Naziat/79:40-41), tentang maqom-maqom (QS. al-Hujurat/49:13, al-Nisa'/4:77, al-Nahl/16:127, dan lain-lain), tentang hal (QS. al-'Alaq/96:14) dan juga tentang kondisi-kondisi kehidupan lainnya dalam bertasawuf (QS. Ali Imran/3:175, al-Sajadah/32:16, al-Baqarah/2:218 dan lain-lain). Ayat-ayat ini dan beberapa ayat lain serta hadis-hadis Nabi SAW yang relatif banyak dapat membawa kepada timbulnya ajaran tasawuf dalam Islam. Karenanya tidaklah mengherankan bila Nicholson setelah mengadakan penelitian yang lebih mendalam, ia berbalik teori dan mengatakan bahwa kehidupan kerohanian sufi mempunyai sumber yang kaya dari ajaran Islam itu sendiri (Nicholson, 1947, 43)
Dalam realitas historis menunjukkan bahwa kelahiran tasawuf dalam Islam itu bermula atau cikal bakalnya dari gerakan hidup zuhud . Jadi sebelum orang-orang sufi itu berkiprah dalam pentas sejarah, telah ada orang-orang zuhud yang secara tekun mengamalkan dan mengaktualisasikan ajaran-ajaran esoteris Islam, yang kemudian dalam perkembangannya dikenal dengan ajaran tasawuf Islam.
Menurut Abdul Qadir Mahmud (1967,58), istilah sufi belum dikenal pada masa Nabi. Menurut catatan sejarah istilah ini muncul ke pemurkaan karena predikat yang dikembangkan untuk generasi tertentu, misalnya Abu Hasyim al-Kufiy (w. 150 H.) yang diberi gelar sang Sufi pertama. Tapi menurut Said Agiel Siraj, orang pertama yang mendapatkan laqob sufi adalah ilmuwan eksak yaitu Jabir Ibn Hayyan (w. 161 H) (Siraj, 1997,70).
Sebagai suatu bentuk wawasan keagamaan esoterik atau batini, tasawuf sangat menekankan segi keruhanian dalam penghayatan agama Islam. Ini berarti bahwa tasawuf merupakan faktor pengimbang (mizan) bagi fiqh yang banyak menekankan segi hukum yang lahiri, bagi kalam yang lebih berorientasi kepada pembahasan rasional dialektis, dan bagi filsafat yang banyak mengandalkan kemampuan rasio lebih dari pada Kalam. Dari sudut pandang lain, tasawuf juga nampak sebagai reaksi terhadap gejala/fenomena kehidupan lahiriyah atau material yang mewah dan menyimpang dari standar kewajaran. Ini dapat dilihat pada periode awal pemunculannya di mana tasawuf memposisikan diri sebagai gerakan oposisi suci (pious opposition). Para zahid Kufalah yang pertama kali memakai wol kasar sebagai reaksi terhadap pakaian sutera yang dipakai oleh golongan Bani Umayah, umpamanya, Sufyan al-Tsauri (w.135 H.), Abu Hasyim (w. 150 H.) dan Jabir Ibn Hayyan (w. 161 H.). Dan di Basrah, Hasan al-Bashri(w.728 H.) seorang ulama besar yang sangat disegani, melakukan tindakan korektif terhadap penguasa Umawiy yang kurang religius, yaitu Abdul Malik Ibn Marwan (685-705 H). (Madjid, 1992, 254). Gerakan oposisi suci ini juga diikuti oleh sejumlah orang yang berpola asketik (zuhud) lainnya. Kalau kita cermati, apa yang dilakukan oleh Hasan al-Basri dan kawan-kawan itu merupakan hasil ijtihadi dalam rangka mencari jawab terhadap fenomena kesenjangan sosial yang terjadi pada masa itu. Secara otomatis maka model respon kritis, apresiatif yang dilakukan oleh Hasan al-Basri itupun kontekstual dan kondusif pada masa itu. Dan model ekspresi keagamaan semacam inipun absah dalam ajaran Islam.
Dalam perkembangannya sejak abad ke-6 H/ke-12 M., yang menarik adalah praktek yang simpel ini berkembang menjadi konsep spiritual yang elaborate dan terorganisasi dalam bentuk tarekat. Organisasi ini memiliki hirarki kepemimpinan, inisiasi atau baiat, formula dzikir dan sisilah yang diyakini sampai pada sahabat Nabi SAW. Jadi tasawuf yang semula menjadi amalan individu atau pemikiran spekulatif sekarang menjadi terstruktur dan berkembang secara massal. Pasca abad ke-6 H/ke-12 M M, dunia Islam di dominasi oleh tarekat yang mampu memainkan peran besar dalam kehidupan sosial politik ( Hodgson, tt.,204).
Akhirnya, dengan kata yang singkat dapat dikatakan bahwa realitas tarekat dalam pentas sejarah, di samping punyai sisi positif ternyata juga memunculkan sisi negatif yang berupa pesimisme, kultus, sinkritisme, pasif dan eksklusif. Sisi negatif inilah yang secara umum telah mengkristal dalam pikiran umat Islam, sehingga mayoritas umat Islam mempunyai citra negatif terhadap tasawuf atau tarekat itu. Nah, sekarang bagaimanakah caranya untuk menghilangkan citra negatif tersebut. Ini adalah agenda besar yang harus dicari jawab oleh umat Islam. Di sinilah dibutukan sebuah penyegaran atau wacana baru dalam memahami Islam dan tasawuf serta tarekat pada khususnya agar tetap selalu eksis, kontekstual dan kondusif bagi kehidupan global umat manusia.
NEO SUFISME : DARI DEKONSTRUKSI KE REKONSTRUKSI TASAWUF
Pada zaman moderen atau pasca modere ini, tasawuf atau tarekat berada dalam ujian yang amat berat, khususnya ujian epistimologis. Dalam kondisi yang demikian itu, eksisitensi tasawuf baik sebagai kesatuan sistemik dalam kerangka bangunan keilmuan Islam, maupun sebagai bagian integral dalam Islam, mempunyai kedudukan yang sangat strategis, dilihat dari kepentingan pembangunan individu dan komunal, maupun dalam rangka membangun tamaddun Islam . Hal yang disebut terakhir ini seharusnya diletakkan dalam kerangka perekayasaan pemahaman tasawuf sebagai bagian dari Islam. Sehingga Islam tidak hanya sekedar manifestasi simbolik dan verbalis, tanpa adanya visi kultural yang jelas dan pasti. Dalam perspektif masa depan, hal yang demikian ini mutlak diperlukan, agar tasawuf Islam tidak menjadi konsep yang diwarnai oleh idealisme utopis. Untuk itu dinamika pemikiran dalam tasawuf selalu ditantang agar mampu memberikan responnya dalam dunia global, jika eksistensinya ingin tetap selalu diakui.
Neo sufisme sebagai model pemahaman baru dalam dunia tasawuf, sebenarnya bukanlah fenomena yang sepenuhnya baru, sebab dilihat dari segi latar belakang historis sosiologis kelahirannya bisa dilacak sejak abad klasik (650-1250 M), fase pertama (650-1000 M) (Nasution, 1987,13) dan lihat (Noer,1995,1-4), lihat juga (Nafis,1996,291). Yang penting dikemukakan di sini adalah bahwa sejak awal pertumbuhan sufisme sampai setidak-tidaknya munculnya Abu Yazid al-Busthamiy (w.261.H/875 M) dan al-Hallaj (w.309 H/922 M) serta Muhyi al-Din Ibn al-'Arabiy (w.638 H/1240 M) dalam wacana tasawuf yang lebih bersifat falsafi (tasawuf falsafi), terlibat dalam konflik yang tajam dengan literalisme hukum yang diwakili oleh fuqaha'. Di kalangan para sufi sendiri telah mulai timbul gerakan pembaharuan untuk mengintegrasikan dan merekonsiliasi tasawuf dengan syareat, yang oleh banyak ahli disebut sebagai kebangkitan sunni (Sunni Revival), sejak abad ke-3H/9M dan pada paroan abad ke-12M mencapai puncaknya, terjadilah reapproachement yang lebih intens antara Islam yang berorientasi mistik dengan Islam yang berorientasi hukum. Gerakan ini dipelopori oleh al-Kharraz (w.268H/899M), al-Junayd (w.298H/911M), al-Kalabadziy (w.385H/995M), al-Sulamiy (w.1021M), al-Qusyairiy (w.468H/1073M) dan al-Ghazaliy (w.555H/1111M). Dan ada lagi yaitu Ibnu Taymiyyah (w.728H/1328M), al-Simnaniy (w.736H/1336M), Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w.750H/1350M), al-Taftazaniy (w.791H/1389M), Ibrahim al-Biqa'iy (w.885H/1480M), al-Sirhindiy (1034/1625), Ahmad Qushosiy (w.1071/1661), Ibrahim al-Kuraniy (w.1101/1690), al-Sinkiliy (w.1105/1693), Yusuf Muqassariy (w.1111/1699).Dan perlu ditegaskan di sini, bahwa sebenarnya menjelang akhir abad ke-15 M, sufisme mulai diterima sepenuhnya ke dalam pelukan ortodoksi Sunni. (lihat, Noer,1995,1-4, dan Nafis,1996,291-295).
Dilihat dari segi pengaruhnya, di antara tokoh-tokoh sufi ini, yang terbesar dan paling berhasil merekonsiliasi antara orientasi lahiri disiplin ilmu syariat dan orientasi batini disipilin ilmu tasawuf yang pertama adalah al-Ghazaliy yang merupakan tokoh pembaharu tasawuf sunni angkatan pertama. Yang oleh Amin Syukur (1999,38), dimasukkan dalam masa konsolidasi. Melalui pemikiran al-Ghazaliy inilah syariat dan thareqah mengalami perpaduan, dengan hubungan antara keduanya saling menunjang. Dan dalam pembaharuan tasawuf angkatan kedua adalah Ibnu Taymiyyah, yang oleh Amin Syukur (1999,41-41), disebut dengan masa pemurni. Dan oleh Fazlur Rahman (1979,194-5), dikatakan sebagai pioner neo-Sufisme dalam khazanah pemikiran umat Islam.
Menurut Fazlur Rahman Neo Sufisme adalah sufisme atau tasawuf yang telah diperbaharui reformed sufism, terutama dilucuti dari ciri dan kandungan ekstatik metafisiknya dan juga kandungan mystiko filosofis digantikan dengan kandungan yang sesuai dengan dalil-dalil ortodoksi Islam. (Rahman, 1979,205-206). Lebih jauh lagi ia menjelaskan bahwa : Neo Sufisme itu mempunyai ciri utama berupa tekanan kepada motif moral dan penerapan metode dzikir dan muraqabah atau konsentrasi keruhanian guna mendekati Tuhan, tetapi sasaran dan isi konsentrasi itu disejajarkan dengan doktrin salafi (ortodoks), yang bertujuan untuk menegakkan keimanan dan akidah yang benar dan kemurnian moral dan jiwa. (Rahman, 1979, 95).
Gejalah yang dapat disebut neo sufisme ini, cenderung untu menghidupkan kembali aktifisme salafi dan menanamkan kembali sikap positif kepada dunia. Dari sini dapat dikatakan bahwa neo-sufisme sangat menekankan dan berupaya memperbaiki faktor moral asli serta kontrol diri seperti puritanis dalam sufisme. Neo Sufisme juga mengalihkan pusat perhatian kepada rekonstruksi sosio-moral masyarakat muslim. Hal ini jelas berbeda dengan sufisme awal, yang lebih menekankan individu daripada masyarakat .
Dari paparan di atas menunjukkan bahwa karakter keseluruhan Neo-Sufisme tidak ragu lagi adalah puritanis dan aktivis. Dan yang demikian ini sekaligus menjadi ciri-ciri yang melekat pada apa yang disebut Neo-Sufisme. Agar lebih muda untuk memahami essensi Neo-Sufisme, penulis berusaha mengklasifikasikan ciri- ciri utama Neo-Sufisme sebagai berikut :
1. Menjadikan al-Qur’an dan al-Hadits plus ijtihad sebagai dasar pijakannya
2 Mengihidupkan kembali aktifisme salafi dan menanamkan sikap positif kepada dunia.
3. Memusatkan perhatian kepada rekonstruksi sosio-moral masyarakat muslim moderen.
4 .Aksentuasi khusus pada moral dan penerapan metode dzikir dan muraqabah atau konsenterasi keruhanian guna mendekati Tuhan dengan doktrin salafi
5. Mempunyai karakter puritanis dan aktifis.
Dan selanjutnya untuk mendukung konsep ideal nan mulia neo sufisme di atas, aga dapat dimanifestasikan dan diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat moderen atau post moderen ini, maka dekonstruksi terhadap produk doktrin tasawuf lama adalah sesuatu yang mutlak harus dilakukan, dan selanjutnya perlu diadakan rekonstruksi sesuai dengan proyeksi kekiniaan dan kedisinian.
Konsep-konsep yang perlu didekonstruksi dan direkonstruksi atau direformulasi itu antara lain :konsep tentang Zuhud, Tawakkal, dan Uzlah.
1.Zuhud
Zuhud dalam pengertian Barat diistilahkan ascetisisme dan diberi makna sebagai sikap mematikan kesenangan dunia, dan memang mayoritas umat mendefinisikan demikian. Secara etimologis, zuhud berarti raghaba ‘an syai in wa tarakahu, artinya tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Zahada fi al-dunya, berarti mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk ibadah.(al-Yasu’i, tt., 308, Munawir, 1991,626). Pengertian ini boleh jadi diambil dari pengalaman sejarah dunia para zahid yang bergaya hidup sangat sederhana dan menolak segala bentuk kemewahan dalam rangka melenyapkan keterikatan hati dari yang selain Tuhan (Allah)
Pengertian ini sangat statis dan berakibat menjauhi siklus kehidupan duniawi. Jika hal yang semacam ini yang dipertahankan pasti umat Islam akan selalu termarginalkan dalam konstalasi kehidupannya, tidak mendorong untuk berbuat, melumpuhkan kegiatan ekonomi dan mencukupkan diri dengan jiwa Qana’ah sebagai tempat perlindungannya. Dapat dipastikan, yang demikian ini akibat pemahaman yang sepihak dala menangkap pesab moral al-Qur’an, hanya menggunakan justifikasi ayat tertentu (QS. 63:9, 9:55) dan tidak memperhatikan ayat yang lain (QS. 77:28).
Kiranya perlu definisi minimal tentang konsep Zuhd, paling tidak tidak harus meninggalkan kemewahan atau bahkan memalingkan dairi dari segala urusan selain Allah, tetapi cukup meninggalkan dari sesuatu yang haram, seperti yang dikemukakan oleh Ahmad bin Hanbal seperti yang dikutip oleh Abdul Djamil (1993, 9). Hal ini ditegaskan oleh Ibnu Taymiyah, bahwa Zuhud tidak berarti menjauhkan diri dari kehidupan dunia atau meninggalkan perkara yang dihalalkan yang membawa kepada kebaikan yang diutamakan (al-mashlahah al-rajihah). Zuhud yang sesuai dengan syariah (al-zuhd al-masyru‘), ialah meninggalkan perkara yang merugikan atau perkara yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat (al-zuhd fi ma yadlurr la fi ma yanfa‘). (Taimiyah, 1999, 21). Jadi tidak perlu menghalangi manusia untuk melakukan aktifitas yang mensejahterakannya secara material, sebab betapapun untuk konteks sekarang, hal ini tidak dapat dipungkiri. Gerakan sufi perlu diubah ke watak yang kreatif dinamis dan progressif seperti yang pernah terjadi di Sudan, yakni mampu memobilisasi massa untuk menentang kezaliman,atau seperti tarekat Sanusiyah di Afrika Utara yang mementingkan kegiatan ekonomi dan perdagangan serta aspek profesional lainnya. Model-model semacam inilah yang pleh Fazlur Rahman disebut sebagai fenomena gerakan Neo-Sufisme. Jadi yang penting bukan meninggalkan yang selain Tuhan, tetapi membuat Tuhan senantiasa “hadir” dalam diri secara kontinyu dalam aktifitas apapun dan di tempat manapun, bukan yang secara tenporal dirasakan hadir hanya sebatas di tempat-tempat suci.
2. Tawakkal
Seperti halnya Zuhd, tawakkal hapir selalu dipahami dengan pengertian eksklusif. Tawakkal dalam ajaran tasawuf yang berkembang dan dipandang sebagai maqam (station) di mana sang sufi memiliki kepasrahan total terhadap yang dikehendaki Allah. Manusia sebagai hamba dihadapan Tuhan tidak berarti sama sekali dihadapkan pada kekuasaan mutlak Tuhan, nyaris-lenyap kepribadiannya, dan menjadi bukan apa-apa lagi kecuali hanya alat belaka dalam mewujudkan taqdir. (Schimmel, 1986, 191). Contoh yang sering dikutip adalah ungkapan Abu Yazid al-Buethamiy: “ Seandaianya ada binatang buas seperti ular mendekatimu maka engkau tidak perlu berusaha menghindar “.
Pengertian yang didasarkan pengalaman para sufi secara individual tidak tepat manakala dijadikan dalil deduktif untuk menjelaskan makna tawakkal. Harus pula diadakan perbandingan dengan kasus serupa, bagaimana shahabat dahulu menanggapinya. Bukankah khalifah Umar bin Khatthab menghindari untuk masuk kawasan yang terkena wabah penyakit? Dan bukan pula Rasul menyuruh bertawakkal setelah onta itu diikat terlebih dahulu? Dengan demikian pengertian tawakkal ini harus diubah agar supaya tidak berbau fatalis. Tawakkal bukanlah sesuatu tanpa usaha, usaha merupakan sesuatu yang prinsip dalam ajaran agama.
Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa tawakkal tidak berarti meninggalkan sebab dan menyerah kepada nasib (fatalisme). Ia mengkritik orang-orang yang mengaku menyerahkan diri kepada Tuhan, tanpa berusaha dan tidak menjalankan perintahNya. “Mereka menyangka bahwa segala sesuatu telah ditaqdirkan Tuhan, tanpa digantungkan pada sebab-sebab tertentu yang harus diusahakan oleh manusia. Mereka tidak mengetahui bahwa Tuhan mentaqdirkan sesuatu dan menetapkan terjadinya sesuatu dengan sebab-sebab yang dilakukan oleh manusia”. Menurut Ibnu Taimiyah banyak masyayikh yang salah dalam memahami persoalan tawakka. Ia membiarkan dirinya menuruti apa yang ditaqdirkan Tuhan, sementara ia tidak berusaha dan tidak melaksanakan perintah-perintah-Nya . (Taimiyah, 1999, 21-22 dan 28). Pemahaman yang benar terhadap tawakal, ialah dengan memberikan tempat bagi pentingnya usaha, dan serempak pula menyadari akan kemutlakan kekuasaan Tuhan. Dengan kata lain manusia harus berusaha tanpa menyandarkan keberhasilannya kepada usaha yang dilakukannya, melainkan hanya memandang usaha itu sebagai sebab. Penentu keberhasilan tiada lain adalah Tuhan (Taimiyah, 1999, 35 dan 257).
Sebagai langkah awal support terhadap kasb dan ikhtiar secara maksimal patut dihembuskan oleh ruh tasawuf, dan jangan malah mendistorsi akses-akses positif untuk berkembang maju melalui ketentuan yang berlaku menurut hukum alam dan sosial (sunnatullah). Tawakkal hanyalah station terakhir, tanda kepasrahan pasca ikhtiar maksimal manusia.
3. Uzlah
Tentang uzlah ini, sangat perlu dipertanyakan relevansinya untuk masa sekarang ini. Ciri utama tasawuf memang menekankan pada aspek moral untuk tazkiyat al-nafs melalui konsentrasi keruhanian dan sekaligus sebagai bentuk protes terhadap hedonisme dunia seperti saaat munculnya memanglah absah. Namun kiranya protes dengan cara demikian tidaklah tepat untuk masa sekarang. Kontrol yang efektif dapat dilakukan bila pelakunya terjun dan bergumul dengan konstalasi kehidupan yang dihadapi, seraya bisa meluruskan ke tujuan yang luhur dan suci. Nurcholish Madjid menegaskan komitmennya dalam hal ini sebagai berikut :Sesekali menyingkirkan diri (Uzlah) mungkin ada baiknya, tetapi jika hal itu dilakukan untuk menyegarkan kembali wawasan dan meluruskan pandangan, yang kemudian dijadikan titik tolak untuk perlibatan diri dan aktifitas segar lebih lanjut. (Madjid, 1995, 103)
Di sinilah Fazlur Rahman mencatat pentingnya gerakan neo-sufisme tersebut. Gerakan ini cenderung menghidupkan kembali semangat aktivisme salafi dan menanamkan kembali sikap hidup positif terhadap dunia. Dalam konteks inilah kaum Hanbali seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziy sekalipun memusuhi sufisme populer adalah jelas kaum Neo-sufisme dan bahkan bisa dikatakan menjadi pelopor ke arah kecenderungan ini. (Madjid, 1995, 93).
EPILOG
Dalam uraian akhir ini sengaja penulis tidak memberikan kesimpulan final. Penulis hanya mempertegas kembali komitmen dasar yang dapat dijadikan suatu paradigma dalam memahami eksistensi kehidupan tasawuf. Yang pertama; bahwa neo-sufisme itu menekankan perlunya perlibatan dari secara aktif dalam masyarakat secara lebih kuat dari pada sufisme klasik. Kedua, Spiritualisme isolatif yang mengungkung pelakunya dari masyarakat merupakan jenis spiritualisme oreng lemah dan egois, yang tidak tahan menghadapi kejahatan dan bahaya hidup, kemudian lari ke uzlah dalam pengertian yang sempit. Spiritualisme macam ini hanya mencari kebahagiaan diri dan lepas dari tanggung jawab sosial.
Demikianlah beberapa hal yang menarik dan selalu menarik untuk diadakan penelaahan ulang atas konsep-konsep lama yang berkemabng. Jiwa sufi haruslah tetap seiring dengan jiwa agama dan tidak boleh ia menyudut dan membentuk dunianya sendiri. Sebab jikalau ini terjadi dikhawatirkan tasawuf menjadi gerakan semacam kultus atau gerakan fundamentalis, yang malahan berbahaya untuk kelangsungan kemashlahatan umat manusia.
Sampai di sini tasawuf ditantang untuk mampu menyediakan jawaban-jawaban spiritual bagi kebutuhan kehidupan manusia modern yang relevan dengan pola pemikiran yang sedang berkembang. Bagaimanapun manusia modern adalah manusia yang serba kritis, rasional mngutamakan kepentingan kemanusiaan universal dan nilai demokrasi. Pada saat yang sama, lebih menekankan aspek fungsional dan substansial dari pada masalah-masalah simbolisme, formalisme atau ritual-ritual. Pendek kata, letak masa depan tasawuf itu tergantung pada kemampuannya mengartikulasikan diri di tengah-tengah tantangan konstalasi kehidupan umat manusia yang selalu berubah-ubah.
DAFTAR PUSTAKA
Hidayat, Kamaruddin, Muhammad Wahyuni Nafis, Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perennial, Paramadina, Jakarta, 1995
Hodgson, M.G.S., The Venture of Islam, The University of Chicago Press, Chicago, tt..
Madjid, Nurcholish, Khazanah Intelektual Islam, Bulan Bintang , Jakarta, 1984
______, Islam Doktrin dan Peradaban, Paramadina, Jakarta, 1992
______, Islam Agama Peradaban, Paramadina, Jakarta, 1995
Mahmud, Abdul Qadir, al-Falsafah al-Shufiyah fi al-Islam, Dar al-Fikr al-‘Arabiy, Beirut, 1967.
McInner, William, Agama di Abad 21, dalam Ulumul Qur’an, No. 5 Tahun 1990.
Nafis, Muhammad Wahyuni, Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam, Paramadina, Jakarta, 1996
Munawwir, Warson, Kamus al-Munawwir, Pustaka Progresif, Surabaya, 1991
Nasr, S. Husen, Traditional Islam in The Modern World,Kegan Paul, London, 1987
______, Islam and the Plight of Modern Man, Longman Group Ltd., London, 1975
Nasution, Harun, Islam Rasional, Mizan, Jakarta, 1995
______, Filsafat dan Mistisisme dalam Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
Naisbitt, John dan Aburdene, Patricia, Megatrend 2000, Ten New Direction for the 1990’s, Avon Book, New York, 1991
Nicholson, R.A. Fi al-Tashawwuf al-Islamiy wa Tarikhuh, diarabkan oleh Abu ‘Ala ‘Afifi, Lajnah al-Ta’lif wa al-Tarjamah wa al-Nasyr, Cairo, 1969.
______, The Mystics of Islam, Routledge and Kegal Paul, London, 1975
Noer, kautsar Azhari, Ibnu al-Arabi Wahdat al-Wujud dalam Perdebatan, Paramadina, Jakarta, 1995
Rahman, Fazlur, Islam, University of Chicago Press, Chicago, 1979
Schimmel, Annemarie, Dimensi Mistik dalam Islam, terj. Sapardi Djoko Damono, et. Al., Pustaka Firdaus, Jakarta, 1986
Siraj, Said Aqiel, Sufi Pertama Ilmuwan Eksak, Majalah AULA NU, Agustus, 1997
Syukur, Amin, Menggugat Tasawuf: Sufisme dan Tanggung Jawab Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999
Taimiyah,Taqiyuddin Ahmad Ibnu, Majmu’ al- Fatawa, Jilid X, , Dar al-Wafa’, Riyadl, 1999
Al-Yasu’i, Louis Ma’luf, al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab, Katulikiyyah, Beirut, tt..
skip to main |
skip to sidebar
Silahkan Kirim Artikel Anda Kpd Kami bisa melalui Email darussholah@gmail.com
WebLink
Label
- Kata Mutiara (6)
- Keagamaan (52)
- Khutbah Jum'at (15)
- Pendiri Darus Sholah (8)
- Terjemahan Kitab Aswaja (1)
- Tokoh (14)
- Wawasan (3)
Artikel Populer
- KHUTBAH JUM’AT BULAN SYAWAL
- KHUTBAH JUM’AT BULAN SHAFAR
- KHUTBAH JUM’AT BULAN MUHARRAM
- KHUTBAH JUM’AT BULAN DZULQO’DAH
- APLIKASI METODE DISCOVERY LEARNING DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMECAHKAN MASALAH, MOTIVASI BELAJAR DAN DAYA INGAT SISWA
- KHUTBAH JUM’AT BULAN RAJAB
- KEMU'JIZATAN AL-QUR'AN DARI SEGI BAHASA & ISYARAT ILMIYAH
Buku Tamu
Copyright © 2011 Darus Sholah Jember | Powered by Blogger


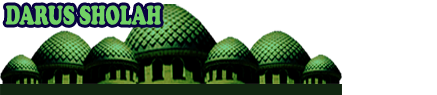
 19.41
19.41
 darussholah
darussholah

 Posted in:
Posted in:
0 komentar:
Posting Komentar