Penulis : azam bahtiar
Membincang soal hukum Islam memang tak akan pernah kering. Di samping itu, kontroversi-kontroversi yang bergejolak di sekitarnya justru malah membuat perbincangan ini makin berwarna.
Dalam rentetan sejarah Islam yang berlangsung lama, porsi besar yang dilahap kajian mengenai hukum tak dapat dipungkiri. Bahkan, menurut Schacht, [1] pengaruh hukum dalam pemikiran umat Islam belum pernah tersaingi, selain oleh tasawuf. Boleh jadi, itulah salah satu keunikan hukum Islam.
Konon, ketaatan terhadap hukum berarti ketaatan terhadap “Tuhan” itu sendiri. Terlepas dari benar-tidaknya statement ini, yang jelas karakteristik hukum Islam dalam cakupannya adalah “siapa anda”, bukan “dimana anda”. Itulah salah satu perbedaan signifikan bila dibandingkan dengan hukum positif.
Statement bahwa ketaatan terhadap hukum berarti sama dengan ketaatan terhadap “Tuhan” ini mendapatkan akarnya secara sempurna dalam perilaku keberagamaan masyarakat di sekitar kita. Misalnya, bahtsul masail yang digelar di pesantren-pesantren yang berbasis NU adalah bukti konkritnya. Entah, apakah bahstul masail hanya sekedar untuk “menemukan”, atau bahkan “mencipta” status hukum, [2] jelas bahwa ia menjustifikasi statement tersebut.
Nah, apa yang kita sebut-sebut sebagai hukum Islam itu tak lain hanyalah sebuah pemahaman. Pemahaman yang merupakan sintesa dari pertempuran seru antara akal dan teks, tanpa menegasikan aspek-aspek lainnya. Karena itulah ia bertitel Fiqh. Walaupun sepenuhnya saya menyadari statement ini masih debatable.
Terlepas dari itu semua, bagaimana sekiranya kita mendengar bahwa klasifikasi hukum Islam yang sudah mapan sekian lama itu, digugat keabsahannya??
Jamal al-Banna
Pemikir gaek asal Mesir, sang negeri piramid ini lahir pada tahun 1920. Jamal adalah putra ahli hadits Mesir, Syaikh Ahmad Abdurrahman Al-Banna, penulis ensiklopedi hadits Al-Fath al-Rabbany fi Tashnif wa Syarh Musnad Al-Imam Ahmad al-Syaibany, dalam 24 volume. Sejak 1989, Jamal menduda. Jamal adalah adik kandung Hasan al-Banna, mursyid dan pendiri Ikhwanul Muslimin. [3] Namun demikian, ia berseberangan dengan pemikiran yang diusung oleh jama’ah al-ikhwan, meskipun sebelumnya ia punya hubungan mesra dengan kelompok yang disebut terahir ini. Jamal adalah doktor jebolan Jami’ah Qahirah (Universitas Kairo). [4] Ia tergolong pembaharu dan pemikir Mesir Garda depan yang produktif. Karya-karyanya sangat banyak, baik yang berupa terjemahan maupun tulisan sendiri, yang melebihi seratus buku, termasuk juga muraja’at . [5]
Itulah sketsa singkat biografi Jamal al-Banna. Saya sadar, biografi singkat semacam ini, belum cukup untuk menebak latar belakang pemikirannya (historical background), sehingga kita dapat dengan mudah menebak alur pikirannya nanti. Hanya saja, tulisan ini memang tidak hendak menyoroti lebih jauh. Agaknya laik disinggung juga di sini adalah bahwa Jamal, dulunya, adalah seorang muslim yang mendambakan berdirinya negara Islam, tak ubahnya para islamis kini, tentunya sebelum akhirnya ia mengalami titik balik pemikiran (semacam epifani). Bahkan bersama beberapa jama’ah al-ikhwan, Jamal pernah dijebloskan ke dalam penjara di Tursina pada tahun 1948. [6] Itulah tokoh kajian kita dalam tulisan ini.
Soal Hukum
Sudah galib kita ketahui bersama, bahwa setiap lini dari perbuatan kita memiliki status hukum tersendiri, dan tentunya ini sudah berlangsung lama. Misalnya, kita dapati Imam al-Syafi’i pernah menyatakan demikian, “Semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan seorang Muslim tentu ada hukum yang jelas dan mengikat atau sekurang-kurangnya ada ketentuan umum yang menunjuk kepadanya. Jika tidak, maka ketentuan hukum itu harus dicari dengan ijtihad, dan ijtihad tak lain adalah qiyas”. [7] Sebenarnya, betulkan demikian adanya??apa saja status hukum itu??inilah yang menjadi keresahan dalam tulisan ini.
Dalam ilmu ushul fiqh, hukm didefinisikan sebagai khithab [8] Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan seorang mukallaf, baik dalam bentuk iqtidha, takhyir, maupun wadh’. Yang dimaksud dengan khithab adalah sifat atau status yang diberikan oleh Allah terhadap apa pun yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, misalnya, seperti dikatakan “berzina itu haram”, artinya ada status ‘haram’ yang dilekatkan terhadap perbuatan berzina. Iqtidha’ adalah suatu tuntutan dari Allah untuk dikerjakan atau ditinggalkan (al-kaff). [9] Sedangkan takhyir adalah wewenang yang diberikan oleh Allah terhadap seorang mukallaf untuk memilih dua opsi, mengerjakan atau tidak. Kemudian, yang dimaksud dengan wadh’ adalah bahwa Syari’ mengikatkan antara dua hal yang berkaitan dengan seorang mukallaf. [10]
Dengan demikian, dalam terminologi ushul fiqh, hukm adalah substansi nas itu sendiri yang muncul dari Syari’ yang menunjukkan tiga poin di atas. Berbeda dengan kalangan ushuly, di lingkungan fiqh, para fukaha memaknai term hukm dengan pengaruh (atsar) dari khithab-Nya. [11]
Lain halnya dengan Muhammad Baqir Shadr, [12] ulama besar syiah ini memaknai hukm sebagai ‘peraturan yang muncul dari Allah untuk mengatur kehidupan manusia’. Khithab syar’i, baik dalam al-Qur’an maupun Sunnah, tak lain kecuali hanya penjelas hukm, bukan hukm itu sendiri. [13] Sebab, tidak selamanya hukm syar’i berkaitan dengan perbuatan mukallaf, namun terkadang ia juga berkaitan dengan diri mukallaf sendiri ataupun hal lain yang berhubungan dengannya. [14] Sekali lagi, lantaran tujuan dari hukm syar’i adalah mengatur kehidupan manusia.
Dengan demikian, menurut Shadr, hendaknya definisi hukm yang terlanjur populer itu diganti dengan; syariat yang datang dari Allah untuk mengatur kehidupan manusia, baik ia berhubungan dengan perbuatan mereka, diri mereka sendiri, maupun hal-hal lain, tentunya selama masuk dalam bingkai kehidupan.
Seberapa pun para pakar ushul fiqh memiliki perbedaan dalam mendefinisikan hukm, agaknya mereka sepakat dalam membagi hukm, secara garis besar, menjadi dua: hukm taklify dan hukm wadh’iy. Hukum taklify adalah khithab yang memuat nilai iqtidha’ dan takhyir, sementara yang mengandung wadh’ dinamai hukum wadh’iy.
KLASIFIKASI HUKUM TAKLIFI
Kaum Ushuliyyun membagi hukum taklifi menjadi lima: [15]
Wajib, yakni apabila tuntutan untuk mengerjakannya berbentuk suatu keharusan (ilzam). [16]
Mandub, yaitu tuntutan jika untuk mengerjakannya bukan merupakan keharusan yang pasti. [17]
Haram, yaitu apa yang syari’ tetapkan atas seorang mukallaf untuk meninggalkannya dan tidak terdapat dispensasi di dalamnya. [18]
Makruh, yakni apabila tuntutan untuk meninggalkanya bukan suatu keharusan yang pasti. [19]
Ibahah, yaitu wewenang yang diberikan oleh Syari’ kepada para mukallaf untuk melakukan suatu pekerjaan atau meninggalkannya tanpa adanya tarjih antara keduanya. [20]
LONTARAN KRITIK
Bila kita perhatikan dengan seksama kutipan Imam Syafi’i di atas, kita dapati adanya suatu keharusan bagi setiap individu Muslim untuk mencari status hukum dari perbuatan dan perilakunya. Oleh karena itu klasifikasi oleh para pakar ushul fiqh terhadap hukum menjadi lima seperti di atas, cukup mewadahi dan menjawab status hukum tertentu dari perbutan mukallaf. Satu hal mendasar yang perlu kita ajukan di sini adalah sebuah pertanyaan “adakah pijakan bagi klasifikasi hukum di atas??”. [21]
Menjawab pertanyaan tersebut, bagi Jamal Al-Banna, klasifikasi hukum yang ada dalam Islam hanyalah tiga, yakni; halal, haram, dan ‘afw. [22] Berbeda dengan para pendahulunya yang membagi hukum menjadi lima bagian; halal, haram, sunnah, makruh, dan mubah.
Dalm rangka mendukung opininya, Jamal menyajikan argumen-argumen sebagai berikut:
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, (justru) menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Qur’an sedang diturunkan, (niscaya) akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan (kamu) tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal yang serupa itu (kepada Nabi mereka), kemudian mereka menjadi kafir.”(al- maidah: 101-102).
“Ataukah kamu hendak meminta Rasulmu (Muhammad) seperti halnya Musa (pernah) diminta (Bani Israil) dahulu ? “(al-Baqarah :108).
Ayat-ayat tersebut juga ayat-ayat yang lain (al-An’am : 138- 140,153, al-A’raf : 32,157, al-Maidah : 103, an-Nahl : 116, Yunus : 59) menyiratkan bahwa hal-hal yang diharamkan dan yang dihalalkan oleh Allah telah dijelaskan sedemikian gamblangnya. Dan ayat-ayat tersebut, lanjut Jamal, menjelaskan dua hal besar, pertama, al-Qu’ran mengecam dengan keras orang-orang yang mengharamkan segala hal baik yang dihalalkan oleh Alllah, kedua, al-Qur’an menyerahkan hak penghalalan dan pengharaman hanya kepada Allah semata. Tidak ada partisipasi dari manusia di dalamnya. Bila rasul melaksanakan hal itu, semata-mata itu dalam bingkai tanggung jawab beliau sebagai Rasul dalam menyampaikan risalah. [23]
Ayat-ayat tersebut menghendaki agar kita melaksanakan apa yang ada dan tidak mencai-cari hal-hal yang memang Syari’ sengaja tidak komentar atasnya. Oleh karena itu, lebih jauh, Jamal menyimpulkan bahwa tahrim munazzal adalah apa yang disebutkan dalam al-Qur’an dengan jelas tanpa adanya ta’wil, atau yang ditetapkan dalam sunnah yang sedikit pun tidak tersentuh virus dha’if. Dengan demikian usaha para mujtahid dalam menetapkan status hukum menjadi halal, haram, atau yang lain meskipun dengan berlandaskan al-Qur’an maupun sunnah namun keluar dari bingkai tahrim munazzal, maka hasil ijtihad tersebut harus diposisikan sebagai bentuk lain yang lebih rendah nilainya dari tahrim munazzal. Bagaimanapun, hasill ijtihad tersebut masih mungkin salah atau tidak sempurna dan tidak bisa dihukumi secara pasti (qath’i) kebenarannya. Bahkan Jamal melangkah lebih jauh lagi dengan menyatakan bahwa menyamakan antara tahrim fiqhi dengan tahrim munazzal adalah satu bentuk syirik yang diisyaratkan dalam al-Qur’an (at-Taubah : 31)
Hal-hal di atas baru menyentuh seputar halal dan haram. Selanjutnya dengan menyajikan beberapa hadis, Jamal menguatkan doktrinya tentang ‘Afw. [24] Coba bandingkan hadis berikut ini dengan pernyataan Imam Syafi’i yang dikutip di awal!
“Cukuplah dengan apa yang aku tinggalkan. Sesungguhnya Umat-umat sebelum kamu binasa disebabkan oleh banyaknya pertanyaan dan perbedaan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Bila kalian aku larang dari sesuatu, maka jauhilah !! Dan bila kuperintahkan dengan sesuatu, laksanakan semampu kalian !!! ” [25]
Lihatlah betapa mencoloknya perbedaan antara sabda Nabi tersebut, sebagai seorang humanis, dengan ucapan seorang faqih ahli hukum ....rasul melarang kita bertanya-tanya, sementara Imam Syafi’i mewajibkan kepada setiap mukallaf untuk mengetahui status hukum dari setiap perbuatannya, yang tak lain adalah dengan bertanya atau mencari. Rasul membatasi agama dengan larangan dan perintah (nahyan wa ijaban). Beliau mengajarkan kepada kaum Muslimin untuk berhenti pada tiap larangan dan melaksanakan perintah sebatas kemampuannya. Ini adalah puncak hikmah di satu sisi, dan rahmat di sisi lain.
Terdapat satu hal lain yang berada di antara wilayah halal dan haram, yang dalam hadis lain disebut ‘awf, “apa yang Allah halalkan dalam kitab-Nya, maka Ia halal, dan apa yang Ia haramkan adalah haram. Dan apapun yang Allah “diam”, maka itu adalah ‘awf. Karena itu, terimalah ‘awf dari Allah, sungguh sekali-kali tidaklah Allah lupa akan sesuatu. Wa ma kana rabbuka nasiyya”. [26] Betapa, elok, wara’, dan lembutnya ungkapan (maka terimalah ‘awf dari Allah). Hadis semakna juga tersebut dalam sabda Nabi yang lain, “yang halal adalah apa yang Allah halalkan dalam kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang Dia haramkan dalam kitab-Nya. Apa pun yang Ia ‘diam’ maka termasuk ‘awf bagi kalian”. [27] Perhatikan, bagaimana Rasul menegaskan (sementara beliau adalah yang mendapat mandat dari Allah dalam tabligh dan bayan) bahwa yang halal dan haram adalah apa yang disebutkan dalam kitabullah ! [28]
Untuk ketiga kalinya, Rasul menyatakan “Sesungguhnya Alah telah menetapkan beberapa kewajiban maka jangan kau campakkan, menetapkan beberapa batasan maka jangan kau lampaui, mengharamkam beberapa hal maka jangan kau terjang, dan “diam” dari banyak hal sebagai rahmat bagi kalian bukan karena lupa, maka janganlah kamu mencari-cari”.[29] Sebagimana al-Qur’an melarang kita untuk bertanya-tanya , begitu juga Rasul menegaskan bahwa, ”Seorang Muslim yang paling besar dosanya adalah seseorang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan atas kaum Muslimin, kemudian hal itu diharamkan sebab pertanyaanya.” [30]
Baiklah, mari kita bandingkan hadis-hadis di atas, baik secara nas maupun makna, dangan apa yang dilakukan para fukaha. Sungguh tampak perbedaan yang amat jauh. Hadis-hadis tersebut hanya membatasi tiga wilayah; halal, haram, ‘awf, dan menjadikan al-Qur’an menjadi tolak ukurnya. Sementara itu kalangan fukaha justru menetapkan adanya lima zona; wajib, haram, nadb, karahah, dan ibahah. Mereka memasukkan ‘awf dalam bingkai hukum-hukum tersebut dan menyerahkan tolak ukurnya kepada para mujtahid, di samping al-Qur’an dan Rasul.
Konklusi
Dari paparan di atas, setidaknya ada tiga poin peting di sini, yang telah disampaikan oleh Jamal al-Banna, yaitu: pertama, jika konsep al-bara’ah al-ashliyyah mendapat porsi yang istimewa dan diletakkan semestinya dalam ushul fiqh, tentu ia dapat merubah citra yang ada selama ini, tentang fiqh. Sehingga, segala sesuatu bisa dikatagorikan sebagai ‘halal’ dan boleh, selama tak ada nash yang mengharamkannya, terlebih lagi bila kita dikaruniai ketentraman hati dalam melaksanakannya. Kedua, tahrim dan tahlil hanya hak Allah semata yang ia sampaikan dengan nash sharih (jelas-gamblang) dan tak membutuhkan upaya takwil, atau sunnah nabi yang tidak memuat virus dha’if. Sedangkan tahrim yang merupakan hasil rekayasa ijtihad para mujtahid, ia memiliki nilai di bawah tahrim munazzal. Mungkin saja ia dikelompokkan dalam perundang-undangan islamy yang tunduk pada perubahan, penghapusan, dan ilgha’ (peng-amandemen-an). Dan ketiga, upaya para fukaha dalam memasukkan beberapa bagian di antara halal dan haram (pada posisi ‘afw, yang telah dikukuhkan oleh banyak hadits) bisa dikatagorikan sebagai kreasi fiqhi dan angan seorang ahli hukum untuk menjangkau segala aktivitas muslim dan menempatkannya di bawah wewenangnya. Sesungguhnya, justru inilah yang ditolak oleh Rasul, dan beliau serah-kembalikan kepada hati umat dan Pencipta mereka. [31]
Bagaimanakah nilai kebenaran dan relevansi pandangan Jamal tersebut???
Wa-Allah a’lam bi al-Shawab.
[1] Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, hal. 1.
[2] Sebagian kalangan memperdebatkan, apakah aktfitas ijtihad hanya sekedar Muksyif ‘an al-Hukm, ataukah Munsyi’? biarlah mereka berdebat, kita tidak usah ikut nimbrung.
[3] http://www.islamiccall.org/the%20islamiccall.html
[4] TEMPO, edisi 30 September 2001, hal: 86.
[5] Untuk daftar karya-karya Jamal, lihat pada bagian belakang Nahwa Fiqh Jadid. Volume 1, hal: 203-208, volume 2, hal: 274-278, dan volume 3, hal: 309-312.
[6] Lihat, Jamal al-Banna, Doktrin Pluralisme dalam al-Qur’an, hal: 39.
[7] Imam Syafi’i, Ar-Risalah, hal: 227. lihat juga, Jamal al-Banna, Nahwa Fiqh Jadid, volume 1, hal: 19.
[8] Penggunan kata khithab mendapat perhatian tersendiri oleh Muhammad Taqi al-Hakim. Bagi dia yang tepat bukanlah khithab, tetapi I’tibar. Sebab, menurutnya, kata khithab tidak mencakup hukm pada masa pembentukan (marhalah al-ja’l), tetapi hanya khusus terhadap fase-fase akhir dari tabligh (penyampaian), wushul (akses), dan fi’liyah (praktis). Oleh karena itu, ia mendefinisikan hukm dengan al-i’tibar al-syar’i al-muta’alliq bi af’alil ‘ibad ta’alluqan mubasyiran aw ghaira mubasyir (concern syariat yang berkaitan dengan aktifitas mukallaf, baik secara langsung maupun tidak). Hal ini dimaksudkan untuk melakukan generalisasi kata al-hukm terhadap segala hal yang di dalamnya terdapat i’tibar syar’i, meskipun pada awalnya tidak berkaitan dengan aktifitas mukallaf. Untuk lebih jauhnya, silahkan merujuk al-Ushul al-‘Ammah lil Fiqh al-Muqaran, hal: 51-53.
[9] Penggunaan term al-kaff juga mendapat kritik dari M. Taqi al-Hakim. Ibid. hal: 53.
[10] Muhammad Abu Zahrah. Ilm Ushul al-Fiqh. Hal: 26-27.
[11] Abdul Wahab Khalaf. Ilm Ushul al-Fiqh. Hal: 100.
[12] Muhammad Baqir al-Shadr. Durus fi Ilmi Ushul: al-Halqah al-Ula. Hal: 40-41.
[13] Menurutnya, hukm adalah madlul al-khithab (arti atau maksud dari khithab), sedangkan khithab sendiri adalah al-kasyif ‘an al-hukm (penyingkap hukm).
[14] Misalnya, hubungan suami istri (‘alaqah zaujiyah) dan kepemilikan (‘alaqah milkiyah), jelas nggak nyambung dengan terma af’al mukallafin.
[15] Ini adalah pandangan mayoritas ulama. Sedangkan kalangan Hanafiyah membedakan antara wajib dan fardhu, dan lain-lain. Sedangkan untuk yang lainnya tidak ada perbedaan yang cukup signfikan. Untuk itu, hukm, menurut mereka ada delapan pembagian. Lihat. M. Taqi al-Hakim. Hal: 63-64.
[16] Muhammad Abu Zahrah, hal: 30-38, Abdul Wahab Khalaf, hal: 105-111, dan M. Taqi al-Hakim, hal: 54-59. Ada banyak klasifikasi untuk term wajib, tergantung dari perspektif mana ia dilihat, namun kesemuanya mengacu pada makna yang sama.
[17] Muhammad Abu Zahrah, hal: 39-42, Abdul Wahab Khalaf, hal: 111-112, dan M. Taqi al-Hakim, hal: 58-59.
[18] Muhammad Abu Zahrah, hal: 42-45, Abdul Wahab Khalaf, hal: 113-114, dan M. Taqi al-Hakim, hal: 59-61.
[19] Muhammad Abu Zahrah, hal: 45-46, Abdul Wahab Khalaf, hal: 114, dan M. Taqi al-Hakim, hal: 61.
[20] Muhammad Abu Zahrah, hal: 46-50, Abdul Wahab Khalaf, hal: 115-116, dan M. Taqi al-Hakim, hal: 61-63. Persoalan apakah Ibahah/Mubah memang ada dalam syari’at Islam??? Terdapat perbedaan sengit di kalangan ulama mengenai hal ini. Konon, al-Ka’by dari kalangan Muktazilah menolak keberadaan hukm mubah. Untuk lebih lanjut, lihat pada buku seperti terdaftar pada catatan kaki no. 15. lihat juga, Jamal al-Banna, Nahwa Fiqh Jadid, Juz 1, hal: 20-23. Lebih menarik lagi bila anda mengikuti diskusi al-Amidi dalam al-Ihkam.
[21] Sampai saat ini, saya belum menemukan landasan teologis yang jelas dan pasti mengenai klasifikasi tersebut, dalam artian nash sharih. Tentunya bukan untuk halal dan haram, tetapi untuk tiga yang lainnya. Mengajukan hadits al-Halal bayyin...., jelas sangat tidak memadai. Dan kenyataannya, klasifikasi demikian kita terima mentah-mentah tanpa bertanya apa basis teologisnya. Sebenarnya, kalau mau diakui, fenomena keberagamaan demikian cukup lumrah di antara kita. Begitulah adanya. Lihat misalnya, Ilmu Ushul al-Fiqh (Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, Muhammad Khudhari Bek), al-Ushul al-‘Ammah lil Fiqh al-Muqaran (M. Taqi al-Hakim), al-Luma’ (Abu Ishak al-Syirazy), Jam’ul Jawami’ (al-Subky), al-Mustashfa (al-Ghazali), Manahijul Wushul (Imam Khomaini), Mabadi Awaliyah, al-Sulam, dan al-Bayan (Abdul Hamid Hakim), Irsyadul Fuhul (al-syaukani), dan al-Dharury (Ibn Rusyd). Dalam kitab-kitab tersebut tidak tercantum landasan teologis seperti yang kami maksud, bahkan al-Syathibi dalam magnum opus-nya ‘al-Muwafaqat’ adem-ayem saja.
[22] Jamal al-Banna. Nahwa Fiqh Jadid, juz1, hal: 20.
[23] Ibid. hal: 16.
[24] Ibid. hal: 19-20.
[25] Lihat juga pembahasan serupa oleh Abdul Wahab al-Sya’rani, dalam al-Mizan al-Kubra, juz 1, hal: 55.
[26] Diriwayatkan oleh al-Hakim dan ia anggap valid (shahih), juga ditkhrij oleh al-Bazzar. Lihat Yusuf al-Qardhawi, al-Halal wal Haram fil Islam, hal:20.
[27] Riwayat al-Turmudzi dan Ibn Majah dari Salman al-Farisi. Suatu ketika Rasulullah Saw ditanya tentang tiga hal; saman (lemak/mentega), jubun (keju), dan al-farra’ (keledai liar), akan tetapi beliau tidak bersedia menjawabnya. Beliau hanya berkomentar dengan hadis tersebut. Beliau tidak bersedia menjawab hal-hal partikular tersebut, adalah agar kita mengembalikannya pada kaidah-kaidah general tentang halal dan haram. Yakni dengan cukup mengetahui apa yang Allah haramkan, maka yang lain tentunya halal. Tentu tak lain tolak ukurnya adalah al-Qur’an. Lihat, Yusuf al-Qardhawi, hal: 20-21.
[28] Sebenarnya, berlindung di balik hadits ini cukup problematis dan debatable. Sebab bagaimana pun, lari pada al-Qur’an sendiri toh juga belum selesai. Artinya tak ada konsesus absolut bahwa suatu ayat, misalnya, memiliki signifikasi dekat atau jauh (dilalah qaribah aw ba’idah) yang mengarah pada sebuah konklusi. Jelas ini multi-tafsir.
[29] Diriwayatkan oleh al-Daruqutni, dan di-hasan-kan oleh Imam Al-Nawawi.
[30] Riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat, Jamal al-Banna, hal: 20.
[31] Jamal al-Banna, hal: 25.
Senarai Bacaan
Al-Qur’an dan terjemahannya. 2005. Dipo Negoro : Bandung.
Al-Banna, Jamal. 1996. Nahwa Fiqh Jadid. 3 volume. Dar al-Fikr : Beirut.
Al-banna, Jamal. 2006. Doktrin Pluralisme dalam al-Qur’an. Menara : Bekasi Timur.
Al-Qardhawi, Yusuf. tt. Al-Halal wal Haram fil Islam. Dinamika Berkah Utama : Jakarta.
Al-Sya’rani, Abdul Wahab. Al-Mizan al-Kubra. Darul Hikmah : Jakarta.
Al-hakim, Muhammad Taqy. 1427 H. Al-Ushul al-‘Ammah lil Fiqh al-Muqaran.
Al-Majma’ al-‘Alamy li Ahlil Bait.
Al-shadr, Muhammad Baqir. 1420 H. Durus fi Ilmil Ushul; al-Halqatul Ula. Wihdah Ta’lif al-Kutub al-Dirasiyah : Qom.
Khalaf, Abdul Wahab. 1991. Ilm Ushul al-Fiqh. Dar al-Ta’lim : Kuwait.
Zahrah, Muhammad Abu. tt. Ilm Ushul al-Fiqh. Dar al-Fikr : Beirut.
Syafi’i, Imam. 1996, Ar-risalah. Pustaka Firdaus : Jakarta.
Schacht, Joseph. 2003. Pengantar Hukum Islam. Islamika : Yogyakarta.
http://www.islamiccall.org/the%20islamiccall.html
skip to main |
skip to sidebar
Silahkan Kirim Artikel Anda Kpd Kami bisa melalui Email darussholah@gmail.com
WebLink
Label
- Kata Mutiara (6)
- Keagamaan (52)
- Khutbah Jum'at (15)
- Pendiri Darus Sholah (8)
- Terjemahan Kitab Aswaja (1)
- Tokoh (14)
- Wawasan (3)
Artikel Populer
- KHUTBAH JUM’AT BULAN SYAWAL
- KHUTBAH JUM’AT BULAN SHAFAR
- KHUTBAH JUM’AT BULAN MUHARRAM
- KHUTBAH JUM’AT BULAN DZULQO’DAH
- APLIKASI METODE DISCOVERY LEARNING DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMECAHKAN MASALAH, MOTIVASI BELAJAR DAN DAYA INGAT SISWA
- KHUTBAH JUM’AT BULAN RAJAB
- KEMU'JIZATAN AL-QUR'AN DARI SEGI BAHASA & ISYARAT ILMIYAH
Buku Tamu
Copyright © 2011 Darus Sholah Jember | Powered by Blogger


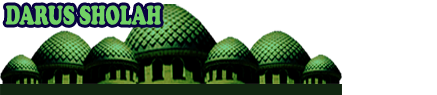
 08.14
08.14
 darussholah
darussholah

 Posted in:
Posted in:
0 komentar:
Posting Komentar