Penulis : Ahmad Daniyal
Manusia adalah makhluk sosial, demikian Ibnu Kholdn menulis dalam salah satu ruas magnum opus-nya, \"al-Muqaddimah\". Dari ungkapan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa nurani setiap manusia membutuhkan sebuah lingkungan, teman, dan perangkat-perangkat sosial lainnya. Jika sebuah komunitas sosial sudah terbentuk, maka secara intuitif, komunitas tersebut merindukan sebuah tatanan yang mengikat dan yang membebaskan sekaligus. Bebas sebagai individu yang sempurna dan terikat karena ia juga include dalam tatanan yang disepakati bersama. Apabila seperti itu karakter setiap manusia, maka adalah wajar jika dalam menurunkan syari\'at, Allah membedakan antara umat yang satu dengan lainnya.
\"Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur\'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu\". (Al-Maidah ayat 48(
Dalam Islam dikenal istilah fikih. Terminologi umum dari fikih adalah sebuah upaya mamahami dan menggali nilai-nilai yuridis dalam syari\'at Islam (Al-Ilmu Bi al-Ahkami al-Syar\'iyyati al-\'Amaliyati al-Muktasabu min Adillatiha al-Tafhshiliyyati). Kalimat al-Mukatasab dalam definisi fikih menjadi sifat dari al-Ilmu, sehingga harus dibca rofa\' (baca: al-Ilmu al-Muktasabu). Karena baik secara gramatikal dan maknanya, kalimat al-Muktasab tidak relevan menjadi sifat dari kalimat al-Ahkam.
Meski demikian, hukum-hukum fikih berbeda dengan hukum-hukum konvensional (qnn). Perbedaan itu bukan hanya pada sumber dan porosnya, tetapi dalam tema dan jangkauanpun tak sama. Fikih memiliki cakupan yang lebih luas. Fikih tidak hanya memandang manusia sebagai makhluk sosial yang harus dikontrol dengan batas-batas agama saja, tetapi gerak-gerik politik, ekonomi, dan budayanya juga ia \'ricuhi\'. Oleh karena itu, semua tindak-tanduk seorang Muslim selalu mendapat perhatian dari fikih, mulai dari makan, kawin, cebok hingga kentut (semua bersifat pribadi). Bahkan, dalam batas-batas tertentu orang non-muslim juga masuk dalam target bahasan fikih (Ahkam Ahl Dzimmah).
Dari paparan singkat di atas, dapat dipahami bahwa posisi fikih atau ilmu fikih sangat dominan dalam peradaban Islam. Posisi yang dominan ini tentu tidak menafikan bidang-bidang lain yang juga urgen, seperti ilmu tafsir, hadits, tasawuf dan lain sebagainya. Urgensitas fikih juga semakin dirasakan bersamaan dengan makin pesatnya perkembangan umat Islam. Lebih-lebih, tuntutan besar juga harus diemban oleh setiap faqh dan mujtahid dalam memenuhi dan mengimbangi arus tersebut. Usaha-usaha ijtihad yang dilakukan oleh masing-masing faqh, tentu tidak bisa lepas dari silsilah sejarah perjalanan fikih itu sendiri. Di mulai dari lahir dan terbentuknya fikih di Hijaz, hingga perkembangannya yang begitu cepat, merayap hampir ke seluruh bentangan penjuru. Oleh karena itu, mengetahui sejarah fikih adalah prasyarat sebuah ijtihad. Mengapa? Seperti yang ditulis oleh Dr. \'Ali Hasan Abdul Qdir, bahwa studi tentang fikih tidak akan menemukan relevansi dan kebenarannya, kecuali dengan mengetahui sejarah fikih berikut realitasnya. Hal itu dapat dilakukan dengan merangkai tema-tema fikih sesuai dengan ruang, waktu dan latar yang berbeda-beda.
Secara periodik sejarah pembentukan fikih dapat dibagi menjadi tiga bagian. Pertama; periode permulaan, yaitu periode awal Islam hingga berkuasanya Bani Umayyah. Pada periode ini, fikih masih berada pada bentuknya yang sederhana. Baik dalam metodologinya maupun sumber dan permasalahannya. Kedua; periode pembentukan, yaitu sejak berkuasanya Bani Umayyah hingga runtuhnya rezim tersebut. Ketiga; periode kebangkitan fikih, periode ini dimulai dari berkuasanya Bani Abbasiah hingga abad ke-3 Hijriah. Namun jika dilihat secara geografis dan sosiologis, masih dalam bentang periodisasi, fikih mengalami dua fase. Yaitu sebelum futhat \'Umar Ra. dan pasca futhat. Sebelum futhat, fikih yang ada hanyalah fikih Hijaz (Mekkah dan Madinah). Tetapi setelah masa-masa futhat, fikih Kufah, Bashrah, Syam, Mesir dan Andalusia mulai muncul dengan corak dan warna yang beragam.
Oleh karena itu, menurut penulis, mengetahui dengan seksama kedua model analisa di atas (secara periodik, geografis dan sosiologis) sama-sama penting dalam menguak tabir teritorial sebuah fikih yang menjadi tema makalah ini. Dengan demikian penulis, dalam mengetengahkan fikih teritorial ini, menjalani beberapa tahapan. Pertama, mengulas secara singkat- bingkai sosial yang melatarbelakangi muncul dan berkembangnya fikih secara periodik dengan menonjolkan perbedaan antara periode satu dengan lainnya. Kedua, melacak pengaruh setting sosial pada pembentukan fikih dan ijtihad ulama, sesuai dengan tiga periodesasi di atas. Semuanya dalam rentang waktu yang terbatas, yaitu mulai abad 1 hingga 3 Hijriah.
Fikih dan Setting Sosial
Meski istilah fikih belum muncul, masa nabi Muhammad Saw. adalah masa lahirnya fikih. Pada masa ini, fikih masih dalam bentuknya yang sederhana. Fikih saat itu hanya berusaha merubah tatanan bangsa Arab yang masih lekat dan identik dengan jahiliyah. Pada masa jahiliyah, Arab masih belum mengenal suatu hukum yang disepakati bersama. Saat itu yang menjadi standar dari komunitas Arab adalah adat. Tidak ada hukum pasti yang harus ditaati dan diikuti bersama. Ketua adat atau hakim adat saat itu memang sudah ada. Tetapi jika terjadi pelanggaran sosial maka adatlah yang menentukan segalanya.
Kedatangan Islam membawa perubahan mendasar bagi Arab. Selain akidah tauhid dan konsep moral, Islam juga menawarkan sekawanan hukum-hukum, baik yang berhubungan dengan ibadah, muamalah, pidana dan lain-lain. Namun jika kita lihat, hukum-hukum al-Qur\'an yang ada dalam ayat-ayat ahkm ataupun sunnah Nabi, semuanya tidak lepas dari adat komunitas Arab saat itu. Tema-tema yang dibawa semisal jihad, riba, poligami dan lainnya adalah background turunnya al-Qur\'an. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial tanah Arab turut mempengaruhi turunnya al-Quran. Oleh karena itu, pada awal Islam selain al-Qur\'an dan sunnah Nabi, adat (al-\'urf) juga menjadi sumber pegambilan dan pertimbangan hukum.
Setelah Nabi wafat, para sahabat mewarisi dan segera menggantikan kepemimpinan Nabi. Para pemimpin itu kemudian dikenal dengan Khulaf\' ar-Rsyidn. Pada masa ini terutama pada masa khalifah Ab Bakar- fikih masih belum mengalami perubahan-perubahan radikal. Permasalahan-permasalahan yang ada dapat diselesaikan oleh para faqh saat itu. Meski demikian, perbedaan pendapat sering terjadi di antara mereka. Namun, perbedaan yang terjadi bukan disebabkan oleh kondisi sosial yang berbeda, karena para sahabat mayoritas masih berdiam di Hijaz. Secara umum perbedaan yang terjadi disebabkan oleh interpretasi terhadap al-Qur\'an, bekal hadits, dan ijtihad sebagai sumber hukum- para sahabat yang berlainan. Contoh kongkrit adalah permasalahan pemberantasan kaum murtad, soal kodifikasi al-Qur\'an, masalah waris, talak dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh semacam Ab Bakar, \'Umar, Utsmn, \'Ali, Ibnu Mas\'d, Mu\'dz bin Jabal dan lainnya, sering mewarnai perdebatan mereka.
Pada masa \'Umar Ra., pemerintahan Islam berhasil melakukan ekspansi dan futhat gemilang. Ekspansi \'Umar di mulai dari Irak pada tahun 14 H. dan di akhiri di Khurasan pada tahun 23 H. Secara umum pasukan \'Umar tidak pernah mengalami kekalahan berarti. Semua ekspansi berhasil, baik secara damai maupun dengan pertempuran. Nah, berawal dari futhat ini fikih, juga ilmu-ilmu lain semisal tafsir dan lainnya, mengalami perubahan-perubahan mendasar, terutama pada cakupan dan tema-tema bahasannya. Pertemuan antara Islam dan gugusan peradaban lain seakan memaksa para sahabat untuk memperluas wawasan fikih mereka. Dari fikih Hijaz menuju fikih-fikih yang lain. Oleh karena itu, secara mendasar fikih paska futhat memiliki relevansi yang sama dengan fikih masa nabi. Yaitu mengunakan adat sebagai tolok ukur sebuah hukum, di samping al-Qur\'an, Sunnah dan ijtihad. Dengan futhat, Islam (al-Qur\'an) seakan turun kembali dari langit, dengan teks yang sama tetapi pada konteks (goegrafis dan sosiologis) yang berbeda. Di wilayah Irak, Islam bertemu dengan peradaban Persia, di Mesir dan Syam dengan peradaban Romawi.
Di samping itu, wilayah-wilayah ekspansi memiliki perbedaan mendasar dengan kondisi Arab saat al-Qur\'an turun, seperti tatanan sosial yang maju, mengenal hukum dan berperadaban tinggi. Sehingga fikih, sebagai pemegang otoritas sosial, seolah harus berasimilasi secara cepat dengan peradaban-peradaban baru tersebut. Permasalahan baru segera muncul, mulai dari hal-hal kecil, seperti pengairan, pajak, kriminalitas, hubungan antara orang Islam (sebagai pihak penguasa) dan pihak non muslim (sebagai rakyat) dan lain sebagainya. Dengan demikian, fikih semakin menemukan bentuk dan karakternya. Bahwa fikih adalah air, di mana ia dituangkan maka di situlah ia akan membentuk dirinya. Oleh karenanya, sejak masa-masa futhat itu \'Umar, secara berkala menempatkan para sahabat yang kapabel dalam bidang yurisprudensi di wilayah-wilayah baru tersebut. Semisal Ibnu Mas\'d di Kufah, Ab Msa al-Asy\'ari di Basrah, \'Amr bin \'Ash di Mesir, Mu\'dz bin Jabal, Abu Dard dan \'Uabdah bin Shmit di Syam. Masing-masing wilayah, bersama dengan tokoh-tokoh sahabat yang bertempat di sana memiliki problematikanya tersendiri. Kondisi yang ada mengantarkan para sahabat untuk berfatwa. Dan tidak jarang fatwa di satu tempat berbeda dengan yang lain. Di samping itu, perbedaan setting sosial antara Hijaz dan wilayah baru tersebut membisiki para sahabat untuk mengembangkan metode ijtihad mereka. Karena banyak sekali permasalahan yang tidak dicakup secara detail oleh al-Qur\'an dan Sunnah. Sehingga keberanian mereka untuk lebih mengoptimalkan akal cukup kelihatan. Dengan demikian, fikih mulai berkembang pesat hingga kepemimpinan Khlulaf\' ar-Rsyidn berakhir.
Fikih kembali mengalami pengalaman baru bersamaan dengan berubahnya peta politik dan sistem pemerintahan Islam. Bani Umayyah berhasil nangkring di singgasana kekuasaan. Pada masa ini sistem khilfah dan bai\'at tidak lagi diterapkan seperti awal kemunculannya. Di samping itu latar belakang Bani Umayyah yang berasal dari keluarga bangsawan bukan agamawan- juga memiliki pengaruh dalam menciptakan suasana saat itu. Misalnya, kehidupan keberagamaan, problem keagamaan yang semakin berkembang, tidak menjadi perhatian pemerintah. Hal ini berbeda dengan masa-masa sebelumnya, di mana pemimpin politik juga menjadi pemuka agama. Padahal, kalau kita teliti lebih jauh, hubungan antara umat Islam dan non-Islam dengan berbagai dimensinya- sebagai buah dari futhat, membutuhkan semacam konsep yang Islami dan ijtihad-ijtihad baru.
Bukan hanya itu, beralihnya pusat pemerintahan dari Madinah menuju Syam juga memiliki pengaruh terhadap fikih saat itu. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa Syam adalah pewaris dari peradaban Romawi. Secara langsung maupun tidak, kondisi semacam ini menimbulkan dampak bagi pemerintahan Umayyah dan fikih secara khusus. Apalagi, Romawi saat itu dikenal dengan peradaban yang sudah mapan. Mereka telah mengenal sistem pemerintahan, yurisprudensi, hukum-hukum perkawinan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tokoh-tokoh orientalis semacam Ignaz Goldzier, Joseph Sacht, menangkap indikasi soal adanya pengaruh peradaban Romawi tersebut dalam fikih Islam. Setidaknya istilah peradilan dalam fikih yang menyatakan al-bayyinatu \'al man idda\' wa al-yamnu \'al man ankara, adalah petunjuk jelas bahwa fikih terpengaruh oleh hukum-hukum Romawi. Karena kaidah tersebut telah menjadi aturan baku dalam undang-undangan Romawi.
Seperti yang penulis singgung di atas, bahwa dinasti Bani Umayyah, tidak mencurahkan perhatian yang cukup pada kehidupan keberagamaan saat itu. Hal itu menyebabkan ulama jaman ini lebih cenderung berfatwa dan berijtihad secara solitaire. Bahkan, ulama-ulama yang muncul ke permukaan dapat dihitung dengan jari. Sebut saja \'Umar bin \'Abdul Azz, Sa\'ad bin Laits dan az-Zuhr serta al-Auza\' di Syam. Namun demikian, pada masa ini perkembangan bidang eksakta seperti, sastra, sejarah, dan yang lainnya tumbuh dengan subur. Banyak sekali buku-buku sastra misalnya- juga buku-buku sejarah yang ditulis pada rentang ini. Tetapi yang perlu diingat adalah bahwa periode ini merupakan tahap-tahap pembentukan fikih, terutama di akhir masa-masa pemerintahan Umayyah. Fikih, baik struktur maupun metodologinya mulai mengemuka. Usaha-usaha ini dilatarbelakangi oleh keresahan para ulama Hijaz akan sikap pemerintah yang acuh tak acuh. Itu artinya, fikih kembali mengalami perubahan mendasar yaitu beralihnya konsentrasi ulama dari wilayah realita menuju wilayah teori dan metode. Seperti diketahui bahwa pada masa Rasul dan Khulaf\' ar-Rsyidn, fikih hanya menyelesaikan problem-problem instan yang terjadi di masyarakat. Belum ada satu kaidah umum atau metode matang yang siap untuk dipakai dalam menyelesaikan problematika umat pada masa-masa yang akan datang. Tetapi sejak masa ini, bersamaan dengan birahi politik dinasti Umayyah yang besar dan perhatian yang kecil terhadap ilmu keagamaan dan fikih secara khusus, ulama mulai merasa akan pentingnya sebuah metode ijtihad dalam memecahkan problem-problem kehidupan. Sejak saat ini secara perlahan-lahan- fikih mulai beranjak dari kehidupan nyata dan masuk dalam dunia teori dan metode.
Setidaknya ada dua indikasi yang menandai perubahan orientasi fikih pada periode ini. Pertama, dimulainya kodifikasi sunnah dan hadits. Hadits pada mulanya hanya berupa riwayat-riwayat yang diterima melalui lisan per lisan. Dari Nabi kemudian sahabat, tabi\'in, tabi\'i-t tabi\'in dan seterusnya. Namun pada masa ini, hadits mulai ditulis dan dikodifikasi. Menurut catatan sejarah, orang pertama yang melakukan usaha itu adalah az-Zuhr atas perintah \'Umar bin \'Abdul Azz. Selain kodifikasi, yang juga dilakukan ialah membuat metode penerimaan hadits. Setiap hadits yang diterima harus melalui proses uji yang kemudian dikenal dengan al-jarhu wa at-ta\'dl. Artinya, hadits yang dapat diterima sebagai pedoman hanyalah hadits yang lulus uji, baik trinsmisinya (sanad) maupun muatannya. Lalu, mengapa hadits dikodifikasi dan diuji dengan sedemikian rupa? Adakah kaitan antara hadits dan fikih? Memang, hubungan antara hadits dan fikih memang sangat kuat. Hadits, baik yang shohh maupun yang tidak, pasti mengandung unsur fikih di dalamnya walau terkadang abstrak-. Karenanya, perkembangan fikih pada masa Nabi dapat kita lacak lewat hadits dan sunnahnya. Dengan kata lain, hadits adalah fikih yang terucap. Karenanya jika hadits terabaikan maka secara kausalitatif fikih-fikih Nabi dipastikan hilang. Oleh karena itulah, ulama merasa perlu untuk melestarikan hadits dan sunnah demi keberlangsungan fikih.
Kedua, munculnya madrasah-madrasah fikih. Stabilitas politik yang tidak menentu turut memberikan dampak negatif bagi kenyamanan berijtihad dan belajar. Baik sahabat maupun tabi\'in terutama yang memiliki kapabiltas dalam fikih- merasakan perlunya kontinyuitas dalam fikih. Sehingga secara alami, para sahabat dan tabi\'in yang tersebar di pusat-pusat kekuasaan Islam segera membentuk lesehan-lesehan ilmiah. Mereka mulai mensistemasi fikih, hadits, pendapat sahabat dan pendahulu mereka, kemudian melakukan sikronisasi dengan ijtihad mereka. Di antara tokoh-tokoh madrasah itu adalah, Said bin Musayyib di Madinah, \'Ath\' bin Ab Rabbah di Mekkah, Ibrahm an-Nakha\'i di Kufah, Hasan al-Basri di Basrah, Makhl di Syam dan Thws di Yaman. Seiring dengan lahirnya madrasah-madrasah itu, muncul pula variasi dalam berijtihad dan berfikih, sesuai dengan karakter masing-masing tempat dan tokohnya. Perbedaan yang paling kentara dan sesekali meruncing adalah antara madrasah Madinah (Hijaz) dan Madrasah Kufah (Iraq). Demikianlah, kondisi fikih pada masa dinasti Umayyah. Sehingga dapat ditarik benang merah, bahwa fluktuasi politik dan pemerintahan yang sekuler sangat mempengaruhi pembentukan dan perkembangan fikih serta model ijtihad para ulama saat itu.
Memasuki abad ke-2 Hijriah fikih semakin beranjak dewasa dan hampir menemukan betuk finalnya. Para sejarawan sering menyebut abad ini sebagai masa-masa kematangan fikih. Rangka pikir metodologi fikih yang sudah dimulai pada akhir dinasti Umayyah, kian tampak dan terstruktur bersamaan dengan runtuhnya dinasti itu dan tampilnya dinasti Abbasiah. Dinasti ini berbeda dengan dinasti sebelumnya. Jika pada kurun yang lalu, ilmu-ilmu keagamaan terabaikan, maka pada masa dinasti Abbasiah yang terjadi adalah sebaliknya. Agama dan negara adalah wujud yang satu. Sehingga, sistem pemerintahan ini membuat ilmu-ilmu keagamaan tumbuh dengan subur. Di samping fikih, bidang-bidang lain seperti ilmu teologi, tafsir, hadits juga mulai terbentuk sebagai satu bangunan pemikiran yang mandiri. Oleh karena itu dengan cepat pula, perkembangan bidang-bidang di atas mendorong lahirnya berbagai aliran pemikiran dalam Islam. Dalam teologi misalnya kita kenal istilah Sunnah dan aliran Syi\'ah, Ahlu al-Hadits dan Ahlu ar-Ra\'yi dalam fikih juga dalam tafsir. Bahkan tidak jarang, muncul cabang-cabang yang beraneka ragam dari aliran-aliran di atas.
Pada masa ini, selain suburnya madzhab-madzhab fikih, tafsir dan teologi, terjadi pula \'tarik tambang\' yang keras dalam politik. Jika pada masa Khulaf\' ar-Rsyidn, pertentangan kubu \'Ali bin Abi Thlib dan Mu\'wiyah bin Ab Sufyn sempat merangsang tumbuhnya tiga aliran yaitu Syi\'ah dan Khawarij dan Sunnah (jumhr), maka pada masa-masa ini perdebatan semakin meruncing. Tetapi karena kemenangan politik selalu berada di pihak Sunnah (jumhr), maka, baik Syi\'ah maupun Khawarij menjadi golongan yang termarjinalkan (al-Muhammasy). Bukan hanya dalam bidang politik saja, marjinalisasi ini dalam tempo sekejap merambah ke wilayah-wilayah teologi, fikih, tafsir, dan juga hadits. Oleh karena itu, perkembangan sosial, keilmuan, politik yang terjadi secara alami sempat menjadi warna dari aroma fikih pada masa-masa itu. Dengan demikian, ketegangan sosial yang terjadi secara otomatis akan berdampak pada tersusunnya wawasan berpikir, berteologi, bertafsir dan berfikih setiap aliran. Sehingga, sampai pada tataran ini, akan sulit dilacak apakah perdebatan seputar hadits, ijma\', qiyas, istihsan serta otoritas masing-masing dalam fikih (ushul fikih) hingga masalah-masalah fur\' misalnya- secara definitif hanya masuk dalam bingkai fikih saja? Maka, dari realitas sejarah ini dapat disimpulkan bahwa sejak lahir, fikih sudah berbaur dengan sosial dan dicetak selaras dengan atmosfir zamannya.
Daftar Pustaka
1. \'Ali Hasan Abdul Qdir, Nadrah \'Ammah f Trikh al-Fiqh al-Islmi, Dr al-Kutub al-Hadtsah, Kairo, 1965.
2. Ahmad Amin, Fajrul Islm, Maktabah Nahdah al-Mashriah, Kairo, 1975.
3. Syibli an-Nu\'mni, Srah al-Frq, al-Majlis \'A\'l Li ats-Tsaqafi, Kairo, 2000.
4. Ahmad Amin, Duha al-Islm, Maktabah Usrah, Kairo, 1998.
5. Muhammad Abied al-Jabiri, Takwn al-\'Aql al-Arab, al-Markaz at-Tsaqafi al-Lubnani.
6. Dr. Muhammad Zuhaili, Tarikh al-Qadha fi al-Islam, Dar al-Fikr al-Mua\'shir, 2001.
7. Zhid al-Kautsari, Fiqh Ahlil Iraq wa Haditsuhum, Maktabah Azhar li at-Turats, Kairo, 2002.
8. Dr. \'Abdul Majd Mahmd Abdul Majd, al-Ittijahat al-Fiqhiyyah \'inda Ahli al-Hadits, Maktabah al-Khonji, Kairo, 1979.
9. Ignaz Goldzier, al-Islam Aqidah wa al-Syari\'ah.
skip to main |
skip to sidebar
Silahkan Kirim Artikel Anda Kpd Kami bisa melalui Email darussholah@gmail.com
WebLink
Label
- Kata Mutiara (6)
- Keagamaan (52)
- Khutbah Jum'at (15)
- Pendiri Darus Sholah (8)
- Terjemahan Kitab Aswaja (1)
- Tokoh (14)
- Wawasan (3)
Artikel Populer
- KHUTBAH JUM’AT BULAN SYAWAL
- KHUTBAH JUM’AT BULAN SHAFAR
- KHUTBAH JUM’AT BULAN MUHARRAM
- KHUTBAH JUM’AT BULAN DZULQO’DAH
- APLIKASI METODE DISCOVERY LEARNING DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMECAHKAN MASALAH, MOTIVASI BELAJAR DAN DAYA INGAT SISWA
- KHUTBAH JUM’AT BULAN RAJAB
- KEMU'JIZATAN AL-QUR'AN DARI SEGI BAHASA & ISYARAT ILMIYAH
Buku Tamu
Copyright © 2011 Darus Sholah Jember | Powered by Blogger


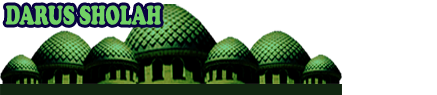
 06.33
06.33
 darussholah
darussholah

 Posted in:
Posted in:
0 komentar:
Posting Komentar